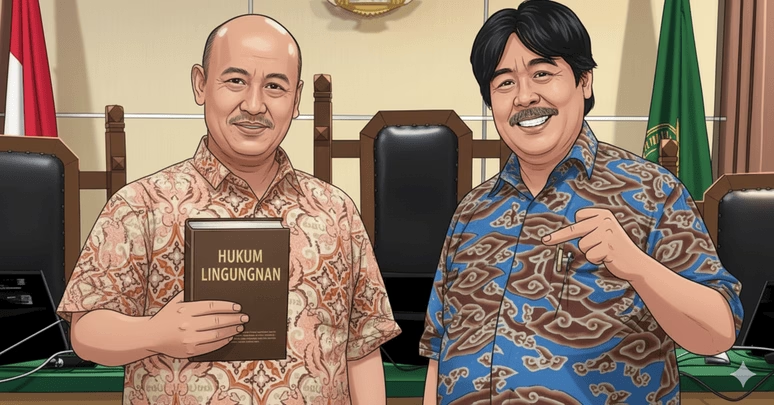Greenpeace dan CELIOS menyatakan, memprioritaskan gas bumi dalam dokumen perencanaan energi seperti RUPTL 2025–2034 adalah langkah mundur.

Laporan riset terbaru Center of Economic and Law Studies (CELIOS) dan Greenpeace Indonesia (2025) membeberkan bukti kuat bahwa gas bumi bukanlah solusi bersih bagi masa depan energi Indonesia. Kajian ini mematahkan mitos gas bumi sebagai “bahan bakar transisi” dan menegaskan bahwa energi baru terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan air menawarkan solusi yang lebih ramah lingkungan, sehat, dan berkelanjutan.
Laporan berjudul “Mengapa Ketergantungan Gas Fosil Menghambat Transisi Energi Bersih?: Dampak Ekonomi, Kesehatan, dan Lingkungan Ekspansi Pembangkit Gas Fosil” itu menegaskan, penggunaan gas bumi akan memperpanjang ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil, memperburuk dampak lingkungan, dan menimbulkan beban ekonomi serta kesehatan yang signifikan.
Sementara itu, energi terbarukan terbukti menghasilkan manfaat ekonomi dan ekologis yang lebih besar dengan biaya yang kian kompetitif.
Laporan ini ditulis tim dari CELIOS dan Greenpeace Indonesia Bhima Yudhistira Adhinegara, Shafa Kalila Aryanti, dan M. Bakhrul Fikri. Para penulis menyatakan, gas bumi selama ini diklaim sebagai bahan bakar bersih karena emisi karbon dioksidanya lebih rendah dibanding batu bara. Namun, laporan ini menunjukkan bahwa klaim tersebut menyesatkan.
Dalam periode 20 tahun, metana yang merupakan komponen utama gas bumi, memiliki potensi pemanasan global 82,5 kali lebih besar dibanding CO₂. Emisi metana terjadi sepanjang proses ekstraksi, pengangkutan, dan pembakaran gas bumi. Tanpa pengendalian ketat, emisi ini akan menghambat pencapaian target Net Zero Emission Indonesia pada 2060.
Dalam skenario ekspansi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) sebesar 2,68 GW, emisi karbon dioksida akan bertambah sebesar 5,97 juta ton per tahun dan emisi metana mencapai 5.332 ton per tahun. Jika kapasitas PLTG ditingkatkan hingga 22 GW sebagaimana tercantum dalam rencana energi nasional, emisi CO₂ akan melonjak hingga 49,02 juta ton per tahun, sementara emisi metana mencapai 43.768 ton per tahun. Data ini bersumber dari analisis Greenpeace dan CELIOS atas estimasi emisi berdasarkan perencanaan proyek-proyek PLTG di Indonesia hingga 2040.
Energi terbarukan: bersih, murah, dan tumbuh cepat
Berbeda dengan gas bumi, energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca selama proses produksi listrik. Potensi energi terbarukan Indonesia juga sangat besar, mencapai 432 GW dari sumber energi surya, angin, dan mikro-hidro. Namun pemanfaatannya belum maksimal.
Data dalam dokumen menyebutkan bahwa melalui skenario pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas, Indonesia bisa meraih manfaat ekonomi yang jauh lebih besar. Selama 25 tahun, kontribusi energi terbarukan komunitas terhadap produk domestik bruto (PDB) diproyeksikan mencapai Rp10.529 triliun.
Total output ekonomi mencapai Rp18.636 triliun, menurunkan angka kemiskinan lebih dari 16 juta orang, menyerap 96 juta tenaga kerja, dan menciptakan pendapatan pekerja sebesar Rp3.645,61 triliun.
Dari sisi efisiensi biaya, pembangkit listrik tenaga surya kini memiliki Levelized Cost of Electricity (LCOE) sebesar USD 0,049/kWh. Angka ini lebih rendah dibandingkan biaya LCOE pembangkit gas bumi yang berkisar antara USD 0,059 hingga USD 0,094/kWh, sebagaimana dicatat dalam laporan Greenpeace dan CELIOS berdasarkan data tahun 2024.
Transisi energi palsu
Alih-alih mempercepat transisi ke energi bersih, pembangunan infrastruktur gas seperti PLTG, terminal LNG, dan jaringan pipa justru menciptakan ketergantungan baru terhadap energi fosil. Biaya investasinya tinggi, waktu pembangunannya lama, dan manfaat ekonominya minim. Dalam simulasi ekonomi nasional yang dilakukan CELIOS, pembangkit berbasis teknologi turbin gas diproyeksikan menurunkan output ekonomi sebesar Rp941,4 triliun dan menyerap 6,7 juta tenaga kerja lebih sedikit dibanding energi terbarukan komunitas.
Selain itu, ekspansi PLTG diprediksi mengurangi PDB sebesar Rp603,6 triliun dan menurunkan pendapatan masyarakat sebesar Rp600,8 triliun selama 16 tahun ke depan. Di sisi lain, energi terbarukan berbasis komunitas justru berpotensi meningkatkan output ekonomi tahunan sebesar Rp205,3 triliun, memperbesar PDB tahunan hingga Rp118,1 triliun, serta meningkatkan pendapatan masyarakat sebesar Rp158,9 triliun per tahun. Energi terbarukan juga menyerap lebih dari 20 juta tenaga kerja secara langsung dan tidak langsung dalam jangka panjang.
Subsidi dan beban kesehatan
Pembangunan pembangkit gas tidak hanya berisiko terhadap lingkungan, tetapi juga menimbulkan beban fiskal melalui subsidi. Berdasarkan estimasi dalam laporan, untuk setiap selisih harga gas sebesar USD 1 per mmbtu, pemerintah harus mengalokasikan anggaran hingga Rp26,7 triliun per tahun hanya untuk menutup biaya operasional PLTG.
Tak hanya itu, dampak kesehatan akibat ekspansi PLTG juga mencemaskan. Dalam skenario pembangunan 22 GW PLTG, biaya kesehatan akibat polusi diperkirakan mencapai Rp249,8 triliun dalam 15 tahun. Beban tambahan terhadap sistem jaminan kesehatan nasional seperti BPJS pun akan meningkat tajam, dengan proyeksi klaim mencapai Rp1.705,9 triliun pada tahun 2040.
Greenpeace dan CELIOS secara tegas menyatakan bahwa memprioritaskan gas bumi dalam dokumen perencanaan energi seperti RUPTL 2025–2034 adalah langkah mundur. Narasi gas sebagai “bahan bakar transisi” tidak hanya menyesatkan, tapi juga mengalihkan sumber daya dari investasi yang seharusnya diarahkan pada energi terbarukan.
Laporan ini menyerukan pembatalan proyek-proyek PLTG baru, revisi kebijakan bauran energi nasional, dan pengalihan subsidi ke pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas. Energi terbarukan terbukti tidak hanya lebih ramah lingkungan, tetapi juga lebih adil secara sosial dan menguntungkan secara ekonomi.