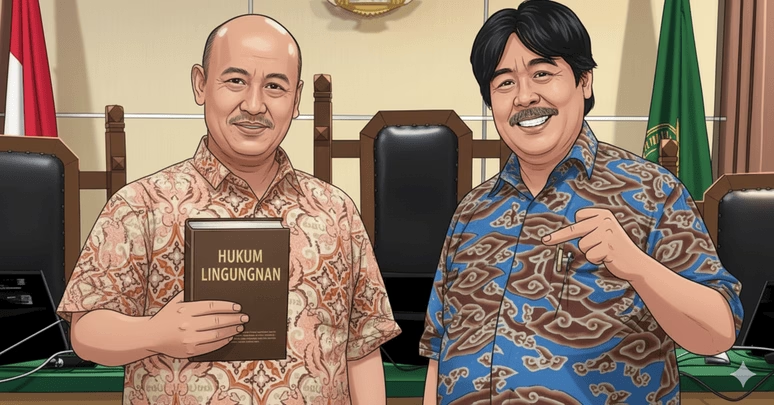Pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas utama dalam strategi pembangunan nasional. Indonesia ditargetkan mampu mencapai swasembada pangan dalam empat hingga lima tahun ke depan. Namun, langkah ambisius ini kembali menempatkan kebijakan food estate sebagai andalan utama, kebijakan yang justru menyimpan rekam jejak penuh masalah di masa lalu.
Kebijakan food estate sejatinya bukan hal baru. Program ini telah dijalankan sejak era Orde Baru dan kembali dihidupkan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam berbagai pelaksanaannya, pendekatan ini lebih sering membawa dampak berbeda ketimbang hasil yang dijanjikan.
Berdasarkan laman Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), food estate menggantikan peran petani dan nelayan sebagai produsen pangan utama, dan menyerahkannya kepada korporasi besar.
Pengalaman masa lalu menunjukkan bagaimana proyek food estate di berbagai daerah justru menciptakan masalah serius. Di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara; Kapuas dan Pulang Pisau, Kalimantan Tengah; serta Merauke di Papua Selatan, program ini menimbulkan perampasan tanah, kerusakan lingkungan, dan kegagalan panen.
Sebagian besar lahan untuk food estate berasal dari kawasan hutan yang dibuka melalui penebangan skala besar. Ini tidak hanya menghancurkan ekosistem lokal, tetapi juga menggusur wilayah dan sumber pangan masyarakat adat. Di banyak tempat, tanah adat diklaim sepihak sebagai “kawasan hutan negara”.
Alih-alih memperkuat posisi petani, kebijakan ini membuka jalan bagi dominasi korporasi besar—baik milik negara maupun swasta—untuk menguasai sektor pangan nasional. Jika arah ini tetap diambil, maka kedaulatan pangan hanya akan menjadi slogan kosong.
Kekhawatiran akan dikuasainya sistem pangan oleh korporasi makin terasa ketika melihat meningkatnya konflik agraria. Dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, tercatat 63 konflik agraria yang berdampak pada lebih dari 10 ribu keluarga. Sebagian besar konflik tersebut berkaitan langsung dengan proyek swasembada pangan dan ekspansi korporasi.
Sepanjang 2024, KPA mencatat 295 konflik agraria dengan luas wilayah terdampak mencapai 1,1 juta hektare, melibatkan lebih dari 67 ribu keluarga. Sektor perkebunan, terutama sawit, menjadi penyumbang konflik terbesar. Petani dan masyarakat adat menjadi kelompok yang paling terdampak.
Kekerasan terhadap warga pun kian marak. Sepanjang tahun lalu, 556 orang menjadi korban kekerasan akibat konflik agraria. Dari jumlah tersebut, 399 dikriminalisasi, dan empat orang tewas akibat tindakan represif aparat.
Padahal sejarah menunjukkan bahwa Indonesia pernah mencapai swasembada pangan pada 1984 tanpa mengandalkan food estate. Saat itu, Presiden Soeharto menggerakkan gotong royong dan memperkuat sentra-sentra produksi padi di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.
Kunci keberhasilan waktu itu terletak pada intensifikasi pertanian, pembangunan infrastruktur irigasi, serta ekstensifikasi melalui perluasan sawah, bukan korporatisasi.
Jika pemerintah serius ingin mewujudkan swasembada pangan, maka ia perlu kembali pada fondasi yang kokoh: pertanian rakyat. Sayangnya, hingga kini, jutaan petani masih menghadapi ketimpangan akses atas tanah.
Data BPS 2023 mencatat sebanyak 17,24 juta petani hanya memiliki lahan pertanian kurang dari 0,5 hektare. Sementara itu, 61,99 juta hektare lahan subur dikuasai oleh perkebunan sawit, hutan tanaman industri, dan tambang.
Reforma agraria sejatinya telah dicantumkan dalam visi-misi Prabowo sebagai bagian dari Asta Cita. Namun implementasinya masih sangat terbatas. Reforma agraria lebih banyak diartikan sebagai program sertifikasi tanah, tanpa upaya redistribusi yang menyeluruh kepada petani dan masyarakat adat.
Tanpa reforma agraria yang sejati, target swasembada pangan hanya akan menjadi ilusi. Padahal penataan ulang penguasaan tanah, penyelesaian konflik agraria, dan perlindungan terhadap petani dan masyarakat adat sebagai fondasi utama kedaulatan pangan.
Masalah lain yang menghambat adalah kebijakan pasar yang tidak berpihak kepada petani. Tanpa pembatasan impor, harga produk pertanian lokal sering anjlok, menyebabkan kerugian besar bagi petani. Banyak dari mereka akhirnya menjual lahannya atau beralih profesi karena tidak mampu bersaing dengan produk impor yang lebih murah.
UU Cipta Kerja juga menjadi penghalang serius bagi reforma agraria. Undang-undang ini mempermudah alih fungsi lahan dan memperkuat peran Badan Bank Tanah untuk kepentingan investasi, bukan redistribusi tanah.
Tanpa keberpihakan nyata terhadap petani dan masyarakat adat, pemerintahan Prabowo berisiko mengulang kegagalan masa lalu. Proyek food estate bukan hanya gagal dalam hal produktivitas, tetapi juga telah meninggalkan jejak konflik dan ketimpangan.
Jika tidak disertai reforma agraria yang menyeluruh, proyek pangan berskala besar hanya akan memperkuat dominasi korporasi dan menjauhkan petani dari tanah dan penghidupan mereka. Maka, pilihannya, apakah ingin mengulang kegagalan masa lalu, atau menempuh jalan baru yang berpihak pada rakyat.