Jatiwangi, sebuah wilayah di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, telah lama dikenal sebagai pusat pengolahan tanah yang mahir. Sejak tahun 1905, masyarakat setempat telah mengolah tanah liat menjadi genteng dan batu bata, sebuah praktik yang tidak hanya membentuk lanskap fisik daerah tetapi juga mengukir identitas dan mata pencarian warganya. Pilihan hidup mereka seakan terbagi dua: menjadi pemilik pabrik genteng, yang dikenal sebagai “jebor,” atau bekerja di dalamnya.
Pada masa kejayaan industri ini, Jatiwangi memiliki sekitar 600 jebor, masing-masing dilengkapi dengan 10 alat pres. Satu alat pres mampu memproduksi lebih dari 2.000 genteng per hari, dioperasikan oleh tim beranggotakan 10 pekerja. Rata-rata, satu jebor dapat menghasilkan omzet antara Rp50 juta hingga Rp100 juta per minggu, dengan upah pekerja sekitar Rp2,5 juta per bulan, menunjukkan betapa sentralnya industri ini bagi perekonomian lokal.
Namun, gejolak ekonomi global pada tahun 1998 membawa mimpi buruk bagi Jatiwangi. Proyek pembangunan nasional yang terhenti dan tumpukan kredit macet menyebabkan jebor berskala besar satu per satu tumbang. Meskipun jebor skala kecil menunjukkan ketahanan yang lebih baik, kini hanya sedikit yang tersisa di Jatiwangi, dan semuanya beroperasi dalam skala kecil, menandai pergeseran signifikan dalam lanskap ekonomi daerah.
Di tengah kebingungan warga menghadapi perubahan zaman dan meredupnya industri genteng, sebuah inisiatif kolektif seni bernama Jatiwangi Art Factory (JAF) muncul pada tahun 2005 di Desa Jatisura. JAF hadir untuk memberikan “jeda”—sebuah ruang refleksi bagi warga melalui seni dan budaya. Tujuannya adalah agar warga dapat menyusun ulang strategi dan membayangkan masa depan wilayah mereka. Pada tahun 2012, JAF menginisiasi Festival Tahun Tanah, dengan Rampak Genteng sebagai simbol utama. Bagi warga, Rampak Genteng adalah “Lebaran Jatiwangi”—sebuah ruang temu bagi warga, seniman, dan pemangku kepentingan untuk menyusun gagasan pembangunan berbasis identitas lokal.1
Arief Yudi, salah satu pendiri Jatiwangi Art Factory, mengungkapkan filosofi di balik pendekatan ini. “Seni menangkap dan menajamkan apa yang ada dalam keseharian. Ia menyumbang tafsir dan rasa pada apa yang dilakukan setiap hari. Maka kita bisa gembira dan berumur panjang karena tidak terpaku pada rutinitas”. Pernyataan ini menegaskan bahwa bagi JAF, seni bukan sekadar hiburan, melainkan alat strategis untuk pemberdayaan komunitas, membantu masyarakat menemukan kembali kegembiraan dan makna dalam kehidupan sehari-hari mereka di tengah perubahan.
Namun, di fase ini pula, gelombang industrialisasi mulai masuk ke Jatiwangi. Industri manufaktur, mulai dari tekstil, garmen, makanan beku, hingga kimia, mulai mendominasi. Banyak jebor dijual kepada investor dan diubah menjadi pabrik, menyebabkan alih fungsi lahan produktif. Pembangunan infrastruktur besar seperti Tol Cipali dan Bandara Kertajati semakin mempercepat arus industrialisasi ini.
Di masa pemerintahan Ridwan Kamil, diluncurkan Koridor Ekonomi Baru Metropolitan Rebana—sebuah proyek strategis nasional yang bertujuan menggantikan dominasi industri Karawang–Bekasi–Bandung Raya yang mulai jenuh. Jatiwangi ditetapkan sebagai salah satu dari 13 kota industri baru dalam proyek ini. Meskipun sektor unggulan yang dicanangkan seharusnya adalah agribisnis dan pergudangan, kenyataannya industri tekstil, garmen, sepatu, dan makanan ringan justru yang mendominasi. Pemerintah Kabupaten Majalengka bahkan telah menetapkan sekitar 900 hektare sebagai Kawasan Industri.
Pergeseran paradigma ekonomi yang terjadi di Jatiwangi ini bukan sekadar perubahan mata pencarian, melainkan sebuah krisis identitas yang mendalam. Identitas Jatiwangi yang kuat sebagai pusat pengolah tanah, yang juga merupakan tulang punggung ekonomi dan budaya masyarakat, kini terancam oleh masuknya industri manufaktur besar dan proyek Metropolitan Rebana. Perubahan ini menciptakan pertarungan antara mempertahankan warisan lokal dan mengejar pertumbuhan ekonomi makro yang seringkali mengabaikan konteks sosial dan lingkungan.
Dalam menghadapi kondisi ini, Jatiwangi Art Factory hadir sebagai katalis transformasi sosial. Kemunculannya di tengah “kebingungan warga” setelah krisis industri genteng menunjukkan bahwa seni dan budaya dapat menjadi “jeda” dan “ruang refleksi” yang krusial. JAF menggunakan seni untuk “mengembalikan kegembiraan warga,” membuktikan bahwa seni tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai alat strategis untuk pemberdayaan komunitas, penyelesaian konflik, dan perumusan visi masa depan yang kolektif. Model yang ditawarkan JAF dapat menjadi studi kasus penting tentang bagaimana inisiatif berbasis seni dan budaya dapat menjadi kekuatan pendorong untuk ketahanan komunitas dan pembangunan berkelanjutan di tengah tekanan modernisasi dan industrialisasi, menawarkan alternatif narasi pembangunan yang lebih holistik.
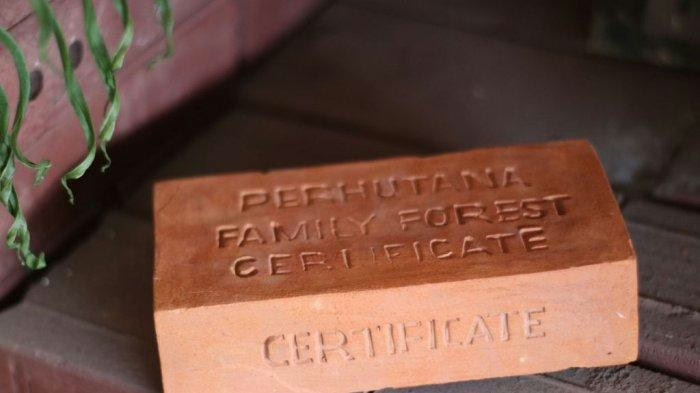
Ketika limbah mengancam sumber kehidupan lokal
Pertumbuhan industri yang pesat di Majalengka, khususnya di bagian utara, membawa konsekuensi sosial dan ekologis yang serius. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan jumlah angkatan kerja dari 651.599 orang pada tahun 2021 menjadi 709.500 orang pada tahun 2024. Namun, peningkatan ini beriringan dengan penurunan kualitas lingkungan yang mencolok.
Warga setempat mengeluhkan bahwa limbah industri dibuang langsung ke sungai, yang merupakan sumber utama irigasi pertanian dan air rumah tangga mereka. Praktik ini secara langsung mengancam mata pencarian petani dan kesehatan masyarakat. Carly, salah satu warga di wilayah Ligung, Majalengka Utara, mengungkapkan kekhawatirannya: “Ini jelas nih, Airnya bau, Berubah warna dan juga hangat”. Ia juga menambahkan bahwa air limbah yang berbau dan hangat seharusnya tidak langsung dibuang ke sungai, mengindikasikan adanya pelanggaran standar pengelolaan limbah.
Dampak pencemaran ini juga dikuatkan oleh Surya Darma, S.H, M.H, penasehat Forum Komunikasi Peduli Daerah Aliran Sungai (FKPDAS) Majalengka. Dia menyatakan, “Kami sangat menyayangkan terjadinya pencemaran ini. Limbah yang meluap ke sawah warga tidak hanya merusak tanah, tetapi juga menyebabkan padi yang ditanam membusuk. Warga juga mengeluhkan gatal-gatal akibat paparan limbah”.
Meskipun ada keluhan warga dan bukti indikasi pencemaran, pihak perusahaan melalui HRD Ifan mengklaim bahwa pengelolaan limbah mereka “sesuai prosedur.” Ifan menjelaskan bahwa air limbah yang telah diolah memang dibuang keluar, dan kemungkinan air hangat serta bau yang tercium berasal dari rembesan, bukan pembuangan langsung. Klaim ini menunjukkan potensi kesenjangan antara praktik di lapangan dan klaim kepatuhan, yang seringkali menjadi celah bagi praktik-praktik yang merugikan lingkungan.
Di samping itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat menemukan indikasi adanya mark-up luas Kawasan Industri Prioritas (KIP) yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) resmi. Kondisi ini membuka potensi konflik tata ruang lintas kabupaten/kota dalam zona Rebana, yang dapat memperparah masalah lingkungan yang sudah ada. Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Metropolitan Rebana, yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2023, memang menyebutkan “Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang” sebagai salah satu sektor ekonomi. Namun, dokumen-dokumen ini tidak secara rinci membahas rencana aksi spesifik untuk pengelolaan limbah industri. Hal ini menunjukkan bahwa fokus kebijakan lebih cenderung pada aspek ekonomi dan infrastruktur daripada mitigasi dampak lingkungan secara komprehensif.
Kondisi di Jatiwangi menggambarkan dilema pembangunan ekonomi versus kualitas lingkungan yang klasik di banyak negara berkembang. Peningkatan angkatan kerja, yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi, secara eksplisit beriringan dengan penurunan kualitas lingkungan. Limbah yang dibuang ke sungai, yang merupakan sumber daya vital bagi masyarakat, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi seringkali mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan lokal. Tanpa regulasi dan pengawasan yang ketat, serta penegakan hukum yang efektif, pertumbuhan industri di Rebana Metropolitan akan terus menimbulkan beban ekologis yang tidak proporsional bagi masyarakat lokal, mengikis modal alam dan sosial mereka. Ini menyoroti kegagalan dalam mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan secara komprehensif.
Selain itu, terdapat kesenjangan yang mencolok antara kebijakan dan implementasi lingkungan. Meskipun perusahaan mengklaim kepatuhan dan adanya badan pengelola Rebana, temuan WALHI Jabar mengenai mark-up RTRW dan keluhan warga tentang limbah menunjukkan adanya diskoneksi antara kerangka kebijakan dan realitas di lapangan. Dokumen rencana Rebana yang minim detail tentang pengelolaan limbah industri semakin memperjelas kondisi ini. Kesenjangan ini menciptakan “zona abu-abu” di mana praktik-praktik yang merusak lingkungan dapat terus berlangsung tanpa akuntabilitas yang memadai. Situasi ini menuntut transparansi yang lebih besar, partisipasi masyarakat yang lebih kuat dalam pengawasan, dan penegakan regulasi yang lebih tegas untuk memastikan pembangunan industri tidak merusak lingkungan secara permanen.
Pengelolaan sampah di Jatiwangi
Masalah sampah di Majalengka, termasuk Jatiwangi, merupakan tantangan yang kompleks. Timbunan sampah di Kabupaten Majalengka terus mengalami peningkatan, dengan Jatiwangi menjadi penyumbang tertinggi sampah rumah tangga. Ini menunjukkan bahwa masalah sampah tidak hanya berasal dari aktivitas industri, tetapi juga dari peningkatan aktivitas domestik seiring dengan pertumbuhan populasi dan ekonomi. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Majalengka memiliki data jumlah tempat pengolahan sampah berdasarkan kecamatan dan diperbarui setiap tahun, mengindikasikan adanya upaya pemantauan terhadap masalah ini.
Secara umum, pengelolaan sampah di Majalengka masih jauh dari harapan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Ini mencakup baik kegiatan pengurangan sampah, seperti konsep 3R (Reduce-Reuse-Recycle), maupun kegiatan penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Bupati Majalengka, menekankan urgensi untuk merancang sistem pengelolaan sampah yang lebih baik, dimulai dari Jatitujuh, dengan fasilitas yang jelas untuk pembuangan sampah yang benar.
Meskipun demikian, ada inisiatif komunitas yang menjanjikan dalam pengelolaan sampah organik. Di Kelurahan Majalengka Kulon, terdapat Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) yang merupakan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKM) Damar. LPM Majalengka Kulon bersama LKM Damar mencanangkan program “Eksplorasi Ekosistem Tata Kelola Sampah Rumah Tangga” sebagai proyek percontohan. Program ini berfokus pada sosialisasi konsep 3R kepada warga dan eksplorasi pemanfaatan sampah di TPS 3R. Pengelolaan sampah organik dilakukan melalui budidaya maggot (larva Black Soldier Fly / BSF) dan pembuatan pupuk organik, di mana bekas media maggot dan pupuk organik diaplikasikan sebagai media tanam.
Inovasi Rumah Maggot, seperti yang telah berhasil diterapkan di Kota Bandung, menunjukkan potensi besar dalam mengolah sampah organik secara efisien, mengurangi volume sampah yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dan menciptakan manfaat ekonomi, seperti menghasilkan pakan ternak berkualitas tinggi. Program semacam ini juga dapat berkolaborasi dengan inisiatif ketahanan pangan lokal.
Selain itu, potensi dan peran bank sampah juga menjadi sorotan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka menyatakan bahwa bank sampah terbukti efektif dalam mengurangi tumpukan sampah di TPA. Sebuah program bank sampah yang dibina oleh PT Pegadaian bahkan memungkinkan masyarakat menyetorkan sampah dan hasilnya dapat dikonversi menjadi emas. Inisiatif ini tidak hanya berkontribusi pada penyelamatan lingkungan tetapi juga membantu perekonomian masyarakat. Meskipun demikian, tantangan dalam mengurangi sampah plastik masih besar. Program percontohan di Pasar Malam Ningxia, Taiwan, yang menargetkan pengurangan sampah plastik sebesar 20% pada tahun 2026, menunjukkan bahwa inisiatif serupa dengan target spesifik dapat diterapkan di Jatiwangi untuk mengatasi masalah ini.
Inisiatif Pengelolaan Sampah Komunitas di Majalengka (Fokus Jatiwangi)
| Nama Inisiatif /Program | Lokasi (Fokus) | Jenis Sampah yang Ditangani | Metode Pengelolaan | Manfaat (Lingkungan /Ekonomi) | Status /Keterangan |
| Program “Eksplorasi Ekosistem Tata Kelola Sampah Rumah Tangga” | Kelurahan Majalengka Kulon | Sampah Organik & Anorganik | Sosialisasi 3R, Budidaya Maggot, Pembuatan Pupuk Organik | Mengurangi timbunan sampah, menciptakan pupuk dan pakan ternak, potensi usaha baru. | Pilot project, menjajaki budidaya jamur dari sampah organik. |
| Bank Sampah Binaan PT Pegadaian | Kabupaten Majalengka | Berbagai jenis sampah (terutama yang dapat dikonversi) | Penyetoran sampah dikonversi menjadi emas. | Mengurangi tumpukan sampah di TPA, membantu perekonomian masyarakat. | Efektif mengurangi sampah. |
Tabel ini menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur dan perilaku masyarakat menjadi hambatan utama dalam pengelolaan sampah. Meskipun ada inisiatif seperti TPS 3R dan bank sampah, pengakuan bahwa pengelolaan sampah “masih jauh dari harapan” dan perlunya Bupati Majalengka untuk “merancang sistem pengelolaan sampah yang lebih baik” menunjukkan bahwa masalahnya bukan hanya kurangnya inisiatif, tetapi juga kurangnya sistem terstruktur, fasilitas yang memadai, serta kesadaran dan partisipasi masyarakat yang belum optimal dalam pemilahan dan pembuangan yang benar. Solusi pengelolaan sampah di Jatiwangi harus bersifat holistik, tidak hanya berfokus pada teknologi atau fasilitas, tetapi juga pada perubahan perilaku masyarakat, edukasi berkelanjutan, dan insentif yang mendorong partisipasi aktif. Kolaborasi antara pemerintah daerah, komunitas, dan sektor swasta menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini.
Lebih jauh, inisiatif seperti budidaya maggot dan pembuatan pupuk organik dari sampah menunjukkan potensi ekonomi sirkular yang signifikan. Sampah, khususnya organik, dapat diubah menjadi sumber daya bernilai ekonomi tinggi, seperti pakan ternak dan pupuk. Mengembangkan inisiatif ini secara lebih luas di Jatiwangi tidak hanya akan mengurangi timbunan sampah tetapi juga menciptakan peluang usaha baru, meningkatkan ketahanan pangan lokal, dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Ini adalah contoh nyata bagaimana masalah lingkungan dapat diubah menjadi peluang pembangunan berkelanjutan, sejalan dengan visi “Kota Terakota” yang berdaulat secara lokal. [Prabowo Setyadi]
Reportase ini didukung oleh Ekuatorial.Com bersama Earth Journalism Network – Internews. Pertama kali terbit di Kapol.ID
- Babi Endemik dari Indonesia yang Terlihat Jelek dan Hampir Punah
- Kuskus Beruang Sulawesi Muncul karena Ancaman dan Tekanan di Hutan
- Deforestasi Penyebab Bencana Ekologis Sekaligus Memicu Ledakan Nyamuk
- Pemerintah Setujui Proyek Geothermal Halmahera Terkoneksi dengan Israel
- Solidaritas kampus dan desakan penegakan hukum menguat pascabencana di Sumatera
- Mengapa Ekonomi Lokal Skala Kecil lebih Tepat untuk Indonesia daripada Industri Ekstraktif?

