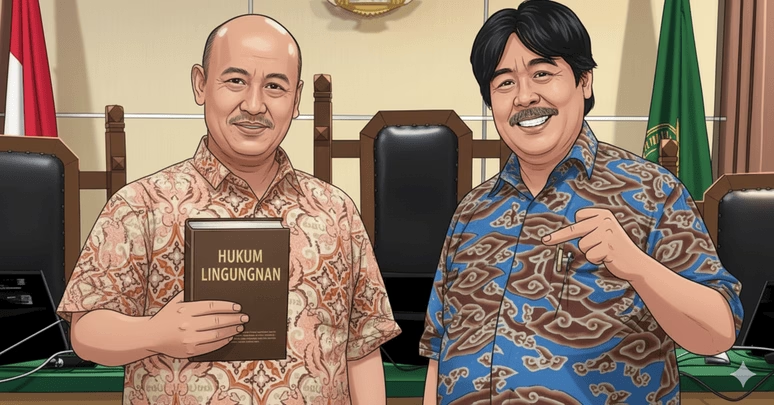Relokasi yang sudah di depan mata, sebuah komunitas di Kepulauan Riau berjuang untuk melindungi desa leluhur dan lingkungan pesisir mereka dari kerusakan.
Rempang Eco City, proyek pembangunan skala besar di Kepulauan Riau bagian barat Indonesia, telah disebut-sebut oleh pemerintah provinsi sebagai ” mesin ekonomi baru bagi Indonesia “. Proyek ini akan mencakup kawasan industri, perumahan, pariwisata, dan suaka margasatwa, semuanya dengan fokus pada keberlanjutan lingkungan, dan bertujuan untuk menciptakan 35.000 lapangan kerja .
Bagi ribuan penduduk Pulau Rempang, lokasi proyek, proyek ambisius ini menjadi sumber kekhawatiran. Proyek ini akan melibatkan penggusuran permukiman yang ada di pulau tersebut, termasuk desa-desa tradisional yang sebagian besar telah dihuni oleh keluarga-keluarga dari beberapa kelompok pelaut Pribumi selama beberapa generasi. Mereka khawatir hal ini akan mengakibatkan hilangnya warisan dan mata pencaharian mereka.
Pemerintah Indonesia mengumumkan Rempang Eco City pada bulan Agustus 2023 dan mewajibkan 7.500 orang yang tinggal di 16 Kampung Tua (desa tua) di pulau itu untuk meninggalkan rumah mereka pada akhir bulan berikutnya. Banyak di antara mereka yang menolak dipindahkan, bentrok dengan pihak berwenang Indonesia saat mereka datang untuk melakukan survei tanah untuk proyek tersebut.
Menyusul kritik terhadap respons polisi selama bentrokan tersebut, pemerintah mencabut batas waktu penggusuran. Pihak berwenang akhirnya meluncurkan program “transmigrasi lokal” untuk memindahkan penduduk ke perumahan baru di Tanjung Banon, di bagian selatan Pulau Rempang, alih-alih memaksa penduduk desa keluar dari pulau sepenuhnya.
Dasar pemerintah untuk relokasi ini adalah karena penduduk desa tidak memiliki sertifikat kepemilikan tanah resmi, mereka bukanlah pemilik sah atas tanah tersebut, meskipun beberapa keluarga telah tinggal di sana sejak abad ke-19. Kritikus seperti Rina Mardiana, pakar sosial-agraria di Universitas IPB, menyebut istilah “transmigrasi lokal” sebagai eufemisme untuk “pemindahan paksa yang menghilangkan hak-hak masyarakat adat”.
Mereka menyebutnya kota ramah lingkungan, tapi hal pertama yang mereka lakukan adalah mengambil tanah yang diwariskan oleh nenek moyang kita, mengambil ruang di mana anak-anak kita seharusnya tumbuh dan berkembang.
Ishaka, resident of Pasir Panjang and coordinator of the Rempang Galang United Community Alliance
Hingga Juni, 106 dari 961 rumah tangga terdampak dilaporkan telah dipindahkan. Namun, perlawanan lokal tetap kuat. Pada pertengahan Agustus, penduduk desa mengintensifkan perlawanan mereka, termasuk menggelar protes terhadap program transmigrasi.
“Mereka menyebutnya kota ramah lingkungan, tetapi hal pertama yang mereka lakukan adalah merampas tanah warisan leluhur kami, merampas ruang tempat anak-anak kami seharusnya tumbuh dan berkembang,” kata Ishaka. Ia adalah warga Pasir Panjang, salah satu desa terdampak, dan koordinator Aliansi Masyarakat Bersatu Rempang Galang (AMAR-GB), sebuah koalisi yang dibentuk oleh warga desa untuk menentang relokasi tersebut.
Awal yang goyah
Dalam kunjungannya ke Tiongkok pada Juli 2023, Menteri Investasi Indonesia saat itu, Bahlil Lahadia, mengumumkan bahwa Indonesia telah mendapatkan komitmen sebesar USD 11,5 miliar dari Xinyi Group Tiongkok untuk pembangunan fasilitas manufaktur panel surya di Pulau Rempang. Ia mengklaim bahwa fasilitas tersebut akan menjadi yang terbesar kedua di dunia.

Namun, pada Februari tahun ini, Xinyi membantah terlibat dalam Rempang Eco City. Dalam pernyataan kepada Pusat Sumber Daya Bisnis & Hak Asasi Manusia, perusahaan menyatakan bahwa “perusahaan belum memulai proyek eco-city apa pun dan belum mencapai kesepakatan atau kontrak apa pun”. Perusahaan juga menyatakan bahwa otoritas terkait “hanya memberikan informasi awal tentang harga dan ketentuan proyek pembangunan kepada perusahaan kami”.
Bulan berikutnya, proyek tersebut mengalami kemunduran lebih lanjut setelah terungkapnya bahwa proyek tersebut dikeluarkan dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) Indonesia, yang menimbulkan pertanyaan tentang prioritas dan kelayakannya. Namun, para pejabat dari Badan Pengelola Kawasan Bebas Batam (BPKB), badan pemerintah yang mengawasi proyek tersebut, secara terbuka menepati komitmen mereka.
Kepala BPKB sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyatakan pada bulan Maret bahwa dikeluarkannya BPKB dari daftar PSN “tidak berarti proyek tersebut tidak berlaku lagi atau telah dibatalkan”. Upaya relokasi masih berlangsung hingga bulan Juli. Warga Tanjung Banon digusur , dan perkebunan mereka diratakan untuk pembangunan rumah bagi program transmigrasi setempat.
Sementara pemerintah melihat peluang ekonomi, warga melihat proyek tersebut sebagai ancaman terhadap keberadaan mereka.
“Masyarakat Rempang memiliki ikatan emosional dan spiritual yang kuat dengan tanah air mereka,” ujar Suraya A. Afiff, seorang ahli ekologi politik di Universitas Indonesia.
Ia mencatat bahwa bagi kelompok-kelompok seperti masyarakat adat Melayu Rempang di pulau tersebut, misalnya, “memaksa mereka meninggalkan [desa mereka] berarti menghapus keberadaan mereka”.
Hilangnya 16 desa adat mereka berarti penduduk, yang keluarganya telah tinggal di sana selama beberapa generasi, akan kehilangan aspek-aspek penting dalam kehidupan mereka. Ini termasuk tanah leluhur yang memiliki nilai spiritual dan budaya yang signifikan, serta tanah pemakaman leluhur .
Hilangnya lahan pertanian dan perkebunan di pulau ini juga dapat berdampak buruk bagi daerah sekitarnya. Sektor pertaniannya merupakan kontributor penting bagi ketahanan pangan dan ekonomi kawasan ini. Pertanian di Pulau Rempang dapat memenuhi sekitar 40-50% permintaan pasar di Batam dan pulau-pulau sekitarnya, ujar Gunawan Satary, Ketua Gabungan Petani Indonesia Kota Batam, kepada The IDN Times .
Gabungan tersebut menekankan bahwa para petani di pulau ini memainkan peran penting dalam mendukung ketahanan pangan lokal dan membantu pemerintah daerah Batam mengendalikan inflasi.
Pulau Rempang juga merupakan surga bagi kehidupan laut dan keanekaragaman hayati. Para peneliti dari Universitas Riau Kepulauan menemukan keberadaan tiga spesies bintang laut dan lima spesies teripang di dua pantai pulau tersebut. Kedua hewan ini sangat berharga karena peran ekologisnya dalam menjaga kesehatan ekosistem laut setempat.
Hutan bakau di pulau ini juga sama pentingnya. Membentang lebih dari 2.800 hektar, hutan bakau menghasilkan nilai Rp75 miliar (USD 4,5 juta) per tahun, menurut studi Universitas Maritim Raja Ali Haji . Sebagian besar nilai ini berasal dari perannya sebagai pelindung pantai melalui pemecah gelombang dan pencegahan intrusi air laut, serta jasa ekologis seperti tempat pembibitan dan tempat mencari makan serta bertelur bagi biota laut.
Kerusakan apa pun pada ekosistem ini akan berdampak langsung pada masyarakat. Pada bulan September, Susan Herawati, sekretaris jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), mempresentasikan penelitian yang belum dipublikasikan yang menunjukkan bahwa potensi kerugian lingkungan akibat proyek Rempang Eco City yang dipaksakan akan mencapai Rp1,3 miliar (USD 78.000) per rumah tangga per tahun bagi penduduk yang tetap tinggal di pulau tersebut, angka yang tiga kali lebih besar dari pendapatan mereka.
Di Tanjung Banon, sejak pembangunan perumahan relokasi dimulai, warga setempat dikabarkan mengeluhkan kerusakan hutan bakau dan kematian ikan di keramba akibat lumpur yang dihasilkan pembangunan, menurut laporan RiauPos.
Miswadi, seorang warga desa Sembulang Hulu di Pulau Rempang dan juru bicara AMAR-GB, mendefinisikan “kota ramah lingkungan” sebagai tempat di mana manusia dan alam hidup berdampingan secara simbiosis. “Namun, yang kita lihat dan dengar justru sebaliknya. Bagaimana ini bisa disebut kota ramah lingkungan jika awalnya justru menghilangkan komunitas yang telah hidup seimbang dengan lingkungan ini selama beberapa generasi?”
Banyak warga tetap bertahan di desa mereka dengan tuntutan sederhana. Mereka menuntut pemerintah untuk mengakui legalitas permukiman yang telah mereka tinggali selama beberapa generasi ini, dan mengupayakan keberlanjutan kehidupan yang damai serta pelestarian budaya mereka.
“Jangan hanya membangun ‘kota ramah lingkungan’,” pinta Ishaka. “Bangunlah masa depan di mana anak-anak kita masih bisa memancing di perairan ini, bercocok tanam di tanah ini, dan menjadikan [ Kampung Tua ] Rempang sebagai rumah mereka. Jika masa depan itu hilang, investasi sebesar apa pun tidak akan bisa mengembalikannya.” [Mohammad Yunus]
Artikel ini terbit pertama kali dengan judul “Indonesian island’s traditional residents face relocation for ‘sustainable’ project” di Dialogue.Earth
- Belajar keberlanjutan dari Kampung Adat Banceuy
- Keanekaragaman hayati dan digitalisasi: Asia Tenggara di persimpangan jalan
- Kerusakan hulu DAS Jambo Aye biang bencana ekologis di Aceh
- Sawah Tangtu pupuk kedaulatan pangan masyarakat adat Kasepuhan Guradog
- Kronologi Penemuan hingga Penguburan Gajah Sumatera Korban Banjir di Pidie Jaya
- Banjir bandang hantam jantung kebun kopi Gayo di Bener Meriah