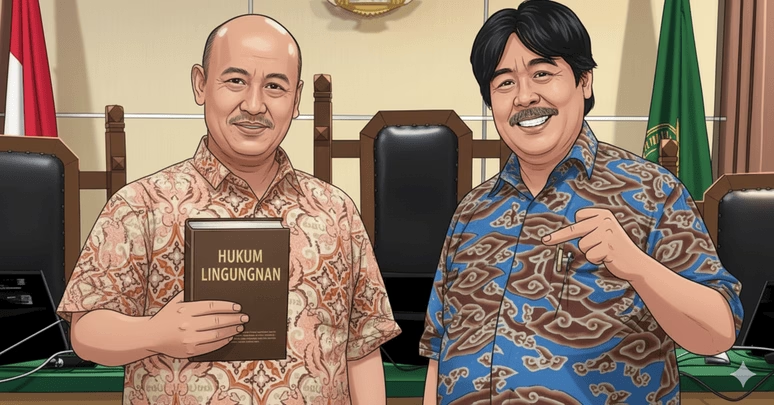Pemerintah Indonesia mengklaim komitmen mengurangi batubara sambil memperluas energi terbarukan di panggung COP 30
Di panggung Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim CoP 30 di Belém, Brazil, narasi iklim Indonesia terdengar meyakinkan. Hashim Djojohadikusumo, yang tampil sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, menjanjikan kepatuhan penuh pada Perjanjian Paris, target Net Zero Emission (NZE) pada 2060, dan visi ambisius pertumbuhan ekonomi 8%. Namun, janji-janji yang berkilauan di panggung global itu disambut dengan skeptisisme tajam dari tanah air.
Di luar ruang negosiasi yang sejuk, Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) menyebut pidato tersebut sarat dengan kontradiksi dan solusi sesat. Bagi mereka, apa yang dipresentasikan di Belém gagal total menyentuh akar masalah ketidakadilan iklim yang selama ini dihadapi rakyat.
Aliansi menyoroti bagaimana klaim pemerintah untuk mengurangi batu bara menjadi hampa ketika pada saat yang sama memperluas bio-bahan bakar dan mempromosikan teknologi kontroversial. Ironi terbesar, menurut mereka, terletak pada aliran dana: komitmen “transisi” terasa palsu ketika subsidi untuk industri kotor, utamanya energi fosil, masih mengalir deras hingga Rp 500 triliun per tahun, jauh melampaui pendanaan untuk aksi iklim yang sejati.
Bagi ARUKI, presentasi di Belém tak lebih dari sebuah fasad yang dirancang untuk menyembunyikan agenda yang sebenarnya.
“Pidato Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi di KTT CoP-30 Belem adalah sebuah pertunjukan sandiwara hijau yang menutupi agenda pro-bisnis,” ujar Torry Kuswardono, Direktur Eksekutif Yayasan PIKUL, yang merupakan bagian dari aliansi.
Kritik tajam Torry merujuk pada promosi solusi-solusi yang oleh pemerintah dibingkai sebagai “transisi bersih”, namun oleh masyarakat sipil dianggap sebagai “solusi palsu”.
“Mereka mempromosikan ‘waste-to-energy’ dan ‘nuclear power’ sebagai transisi bersih. Bagi kami, ini adalah solusi sesat yang merampas ruang hidup dan melanggar HAM, seperti yang terjadi pada proyek geothermal di Poco Leok dan wilayah geothermal lain,” paparnya.
Proyek-proyek ini, yang didorong atas nama energi terbarukan, dalam praktiknya justru menimbulkan konflik baru dengan masyarakat lokal dan adat yang berjuang mempertahankan ruang hidup mereka.
Lebih jauh, ia menyoroti dampak dari kebijakan andalan lainnya, yakni bahan bakar nabati (BBN). Alih-alih menjadi solusi dekarbonisasi, kebijakan ini dituding menjadi dalih untuk perampasan lahan skala besar.
“Kebijakan bahan bakar nabati juga terbukti menjadi dalih perampasan lahan masyarakat adat, komunitas lokal dan petani untuk perkebunan monokultur skala besar, yang hanya memperparah konflik agraria dan mengancam ketahanan lingkungan dan pangan,” tambah Torry.
Program FOLU Net Sink 2030, yang menjadi salah satu pilar utama komitmen iklim Indonesia, juga tak luput dari kritik. ARUKI memandang program tersebut tidak lebih dari sekadar skema offset karbon berskala besar, yang lagi-lagi mengabaikan hak-hak komunitas.
Pada akhirnya, aliansi masyarakat sipil menyimpulkan bahwa solusi-solusi yang ditawarkan Indonesia di panggung global itu gagal mengatasi masalah inti. Pidato di Belém, bagi mereka, adalah cermin pengabaian terhadap keadilan iklim, perampasan lahan yang terus terjadi, dan pengabaian sistematis terhadap hak-hak masyarakat adat serta komunitas lokal.
- Belajar keberlanjutan dari Kampung Adat Banceuy
- Keanekaragaman hayati dan digitalisasi: Asia Tenggara di persimpangan jalan
- Kerusakan hulu DAS Jambo Aye biang bencana ekologis di Aceh
- Sawah Tangtu pupuk kedaulatan pangan masyarakat adat Kasepuhan Guradog
- Kronologi Penemuan hingga Penguburan Gajah Sumatera Korban Banjir di Pidie Jaya
- Banjir bandang hantam jantung kebun kopi Gayo di Bener Meriah