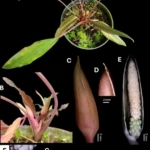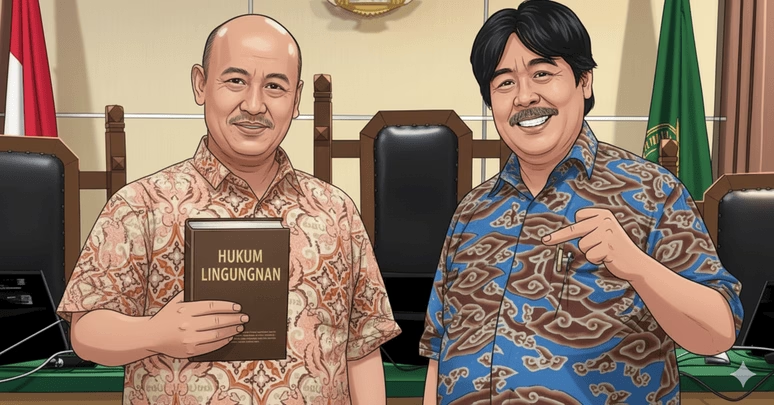Penggalian timah di Bangka dimulai dari abad ke-1. Ratusan tahun timah menjadi komoditas strategis, ratusan tahun itu pula lingkungan terabaikan.
Pada masa lalu, Pulau Bangka pernah memiliki bermacam nama. Mulai dari Vanka (Wangka), Monopin, Mayit-Dong, China Bato, dan Banka. Nama-nama itu tertulis pada buku sastra Hindu abad ke-1 Millndrapantha dan buku suci Hindu-Buddha bernama Nidessa.
Sejarawan George Cœdès juga menyebutkan bahwa sebelum abad pertama, banyak pelaut dari India yang berdatangan ke Wangka—dalam bahasa Sansekerta berarti timah. Sehingga dari ketiga catatan penting itu diduga kuat bahwa penggalian timah sudah ada di Bangka sejak awal abad pertama.
Setelah berabad lamanya, kerajaan-kerajaan kuno juga menyimpan catatan timah di Bangka. Seperti Kerajaan Sriwijaya dengan ditemukanya prasasti Kota Kapur yang bercerita soal penambangan timah di Pulau Bangka pada abad ke-7.
Penggunaan timah saat itu menurut Fakhrizal Abubakar, Kepala Museum Timah Indonesia (TMI) Muntok adalah untuk media barter dan menjadi bahan prasasti. Namun penggalian timahnya masih berskala kecil dengan alat yang sederhana—timah permukaan (timah kulit).
Baru pada masa Kesultanan Palembang di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin I pada 1730-an sampai 1740-an penambangan timah di Pulau Bangka dilakukan secara besar-besaran.
Baca juga: Memulihkan kembali tambang-tambang timah Bangka usai eksploitasi
Ceritanya, Sultan Mahmud Bahaduruddin I menikahi istri muda keturunan Tionghoa dari Johor-Siantan bernama Mas Ayu Ratu Zamnah alias Lim Ba Nio. Kemudian, Zamnah minta dicarikan tempat tinggal baru. Ditunjuklah Kota Muntok di Bangka Barat dan dibangun tujuh rumah untuk Zamnah dan keluarganya dari Johor.
“Muntok adalah hadiah Sultan Palembang untuk Zamnah. Otomatis Muntok menjadi pusat Pulau Bangka dan kemudian menjadi daerah yang spesial (khusus keluarga bangsawan),” Kata Suwito Wu, Ketua Heritage of Tionghoa Bangka.
Nama Muntok sendiri memiliki asal-usulnya. Saat Zamnah melakukan pelayaran, ia menunjuk sebuah daratan. Lalu disebutlah “entok” yang dalam Bahasa Johor artinya “itu”.
Lama kelamaan daerah tersebut bertoponimi Mentok. Lalu perubahan nama lainya mengikuti kemudian. “Muntok adalah ejaan dalam Bahasa Belanda. Mereka tidak bisa mengeja huruf e,” demikian Suwito menjelaskan mengapa Kota Mentok sekarang disebut Muntok.
Setelah Zamnah menempati Muntok, kota itu dibuat lebih teratur dengan pemerintahan dan pembangunan yang pesat. Tokoh yang ditunjuk oleh Kesultanan Palembang untuk mewujudkan harapan itu adalah Wan Akub, paman Zamnah. Ia ditunjuk sebagai kepala negeri dan kepala pertambangan timah di Bangka saat itu.
Produksi timah saat itu tidak besar karena penggalianya masih di permukaan. Wan Akub kemudian memberi usul pada Kesultanan Palembang untuk mendatangkan kuli tambang Tionghoa dari Siam dan Chocin.
Seketika produksi tambang timah meningkat drastis. Sehingga pundi uang Kesultanan Palembang meningkat.
Kesultanan memperkerjakan orang-orang Tionghoa bukan tanpa alasan. Selain lebih disiplin dan bertenaga kuat ketimbang pribumi, mereka mempunyai sistem kolong pada penambangan. Mereka membawa teknologi pacul yang belum dikenal oleh orang-orang pribumi pada 1733.
“Kalau dulu pribumi ambil timah menggunakan linggis ke bawah dengan diameter yang kecil seperti sumur. Tapi Tionghoa beda. Dia bawa alat bernama pacul. Makanya tambang mereka itu besar galianya dan lebar. Yang kita kenal kolong sampai sekarang. Dan dia sudah punya teknologi pompa sederhana dari kayu yang diputar dengan tenaga air seperti kincir,” kata Fakhrizal.
Karena kesuksesan itu, Kesultanan Palembang mendatangkan lebih banyak kuli kontrak dari Selatan Tiongkok yang didatangkan secara bergelombang. “Terutama orang Khek, yang didatangkan saat bujangan yang akhirnya kawin campur dengan pribumi,” kata Fakhrizal.
Orang yang ditunjuk untuk mendatangkan orang-orang Tiongkok bernama Bong Hu But. Kemudian tugasnya digantikan oleh Kapiten Boen A Siong setelah Bong Hu But purna tugas dan kembali ke Palembang.
Boen A Siong ditempatkan di Belo, sekitar sepuluh kilometer ke arah timur Muntok. Kawasan ini menjadi daerah eksploitasi besar-besaran tambang timah pertama milik Kesultanan Palembang.
“Sebagai buktinya kita bisa temukan puing peninggalan klenteng di Belo. Padahal mayoritas masyarakat Belo bukan orang Tionghoa,” kata Suwito. “Ini salah satu jejak orang Tionghoa yang bermigrasi ke pulau Bangka.”
Menurut Fakhrizal, Sultan Palembang pada masa itu menjadi orang terkaya di timur karena penjualan timah. Timah-timah itu kemudian dijual pada kongsi dagang VOC.
“Jadi Sultan Palembang adalah sultan terkaya di Timur. Waktu itu jual sama VOC. Harganya tidak melebihi emas tapi orang perlu sekali dengan timah. Sultan Palembang juga terlibat perjanjian bahwa timah tidak boleh dijual ke tempat lain. Harus VOC,” katanya.
Pada 1811 Inggris menduduki Bangka. Kesultanan Palembang di bawah Sultan Najamuddin menyerahkan Bangka dan Belitung kepada Inggris.
Inggris membentuk residen dan mengubah nama Mentok menjadi Minto. Hubungan dagang Kesultanan Palembang dengan VOC diputus dan digantikan dengan East India Company (EIC)—dengan Lord Minto sebagai Gubernur Jenderal India.
Namun pada 1814 muncul Traktat London I, mewajibkan Inggris untuk menyerahkan Bangka kepada Pemerintahan Kolonial Belanda. Sehingga pada 1816 Belanda menguasai Bangka secara penuh.
Tiga tahun kemudian 1819 Belanda membentuk Banka Tin Winning Bedrijf (BTW), sebuah perusahaan timah milik negara Belanda. Serta menjual timah dengan merek bernama BANKA.

Belanda tetap mengambil pekerja tambang timah dari Tionghoa. Menurut Mary Somers dalam bukunya bertajuk Timah Bangka dan Lada Mentok menyebutkan bahwa pada tahun 1816 terdapat 2.528 penambang Tionghoa dan 2.123 penduduk Tionghoa lainya yang menyebar di Pulau Bangka.
Belanda pun melakukan kemajuan pada mekanisasi penambangan. Yakni sistem pompa air dengan tenaga uap bernama lokomobil. Kemudian muncul tenaga semprot untuk menambang lahan timah.
Namun dalam sejarah pertambangan, kuli kontrak timah memiliki reputasi sebagai kelompok yang sulit diatur. Kerap kali para mandor menjadi sasaran kemarahan kuli-kuli itu menurut Mary Somers.
Pemberontakan kuli tambang yang begitu sohor tercatat berada di bawah pimpinan Liu Nge pada 1889. Pemberontakan ini menolak ketidakadilan yang terjadi di pertambangan. Para kuli kontrak resah dengan upah minim yang dibayar Belanda tidak sesuai dengan yang dijual ke Batavia dengan harga yang tinggi.
Liu Nge merupakan seorang buruh tambang yang memiliki banyak pengikut. Mereka merampas harta milik Belanda. Konon hartanya dibagikan kepada kuli tambang sebagai bentuk suara ketidakadilan. “Mereka menjadi model dari “bandit sosial” semacam Robin Hood,” catat Mary Somers.
Liu Nge kemudian dieksekusi pada 1900 di Mentok. “Dalam catatan Belanda ia digantung, tapi versi cerita mulut ke mulu ia ditembak,” Suwito menceritakan akhir kisah Liu Nge.

Waktu berlalu dan rezim berganti, Jepang masuk dan menguasai Bangka pada 1942. Pertambangan timah pun diambil alih oleh Mitsubishi Kabushiki Kaisha (MKK). Namun penambangan timah masa Jepang tak semanis sebelumnya. Produksinya mengalami penurunan yang drastis.
“Jepang hanya tahu perang. Mereka kurang dalam masalah ini. Makanya produksi turun,” kata Fakhrizal.
Jepang pun kalah dalam Perang Dunia II pada 1945. Tentara-tentara sekutu mendarat ke Bangka melalui Muntok pada 1946. Belanda yang dibonceng sekutu berusaha menguasai kembali penambangan timah. Banka Tin Winning Bedrijf mencancapkan kembali eksploitasi timah di Bangka.
Perang terjadi dimana-mana, tak terkecuali Muntok sampai Pangkal Pinang di masa fase kronik revolusi Indonesia. Belanda pun menyerah menguasai Indonesia. Penambangan timah juga diserahkan ke pemerintahan Indonesia pada 1953.
Perusahaan timah Belanda dilebur kala itu, Namanya berganti menjadi PN Tambang Timah Bangka dan kemudian menjadi PT. Timah Tbk pada 1976.
Masuk pada era Soeharto, Muntok menjadi pusat peleburan timah. Komoditas ini menjadi barang strategis dengan penjagaan yang ketat. “Siapa yang nyelundup ambil timah illegal pasti di penjara,” kata Fakhrizal.
Masa-masa itu, masyarakat tidak bisa menambang karena semua hal yang berkaitan dengan penambangan timah di Bangka dikuasai penuh oleh PT. Timah Tbk. Sampai zaman berganti ketika Soeharto tak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada 1998. Penambangan timah muncul di mana-mana. Siapapun dapat menambang dengan bebas dan muncul istilah tambang inkonvensional (TI) yang bukan dikelola negara. Hal ini terjadi karena timah sudah bukan barang strategis lagi.
Banyak orang kaya mendadak tiba-tiba karena timah. Kebun-kebun yang tadinya dijadikan lahan pertanian dan perkebunan diganti menjadi pertambangan timah pada era 2000-an. Menjadi kolong-kolong yang kita lihat pada hari ini. “Siapa yang punya uang maka ia menambang,” tutur Fakhirzal menceritakan menjamurnya penambang timah awal reformasi.

Menjamurnya penambang timah diiringi dengan aturat ketat yang dikeluarkan oleh PT. Timah Tbk terkait limbah pembuangan timah dan reklamasi.
Namun masih saja aturan itu tidak diperdulikan. Masyarakat yang secara membludak melakukan aktivitas penambangan timah, tidak membuat limbah pembuangan. Alhasil limbah timah dibuang ke sungai-sungai. Lahan-lahan bekas tambang yang sudah tidak berproduksi lagi pun dibiarkan begitu saja. Bahkan, eks-tambang PT. Timah yang sudah direklamasi pun dibuka kembali oleh para penambang illegal.
“Banyak yang liar juga. Seharusnya kan dapat izin usaha, daerah mana yang bisa ditambang. Tapi sekarang ini susah. Cari yang benar benar sesuai izin sesuai izin tambang. Harusnya reklamasi kolong itu tutup. Ini PT. Timah sudah reklamasi dibuka lagi karena alasan perut,” kata Fachrizal.
Saat ini, sungai-sungai di Muntok tercemar limbah bekas timah. Warnanya kecoklatan karena endapan pasir dan membuat volume air naik. Sehingga di musim hujan, Muntok menjadi langganan banjir. Sebaliknya pada musim kemarau, masyarakat kekurangan air bersih karena aktivitas penambangan yang masif.
Aktivitas penambangan dari awal reformasi hingga saat ini membuat nyaris tidak ada lahan-lahan timah baru. Kalaupun ada tambang baru pun belum tentu memproduksi banyak timah.
Banyak para penambang mengalami masa sulit saat ini. Karena lahan tambang yang dimilikinya sudah tidak berproduksi kembali. “Menambang timah ini cepat dapat cepat miskin, cepat kaya cepat miskin,” ucap Fakhrizal yang menjelaskan bahwa bekerja di sektor penambangan timah sudah tidak diminati seperti era jaya di awal reformasi.
Karena lahan di darat sudah sulit, bermunculan fenomena baru di Muntok yaitu penambang laut alias TI apung. Kebanyakan dari mereka adalah pendatang dari Palembang yang memiliki kemampuan menyelam untuk mencari lokasi-lokasi timah di lautan. Namun kegiatan ini ditentang oleh para nelayan karena mengganggu mata pencahariaan mereka.
Para penambang-penambang lama sadar akan masa sulit ini. Beberapa diantaranya mengalihkan bekas tambangnya menjadi pariwisata, perkebunan, pertanian, restoran, dan tambak ikan. Selain berupaya untuk melakukan usaha alternatif, beberapa penambang yakin bahwa cara itu adalah solusi untuk melestarikan lingkungan yang telah dirusak sebelumnya.
Solusi lain untuk mengatasi permasalahan penambangan timah di Muntok saat ini adalah mengambil mineral lanjutan yang dibuang pada limbah timah (tailing). Fakhrizal yang sebelumnya bekerja di PT. Timah Tbk di bagian metalurgi yakin bahwa harga mineral ikutan jauh lebih mahal dibanding timah.
Mineral lanjutan ini diantaranya seperti Quatz, Zircon, Rutile, Ilmenit, Siderite, Xenotime, Monazite, dan Tourmaline. Disebut mineral ikutan (associated minerals) karena mineral-mineral tersebut terbentuk bersamaan dengan proses geologi terbentuknya cassiterite (SnO2).
Di dalam proses pencucian (dressing) dilakukan pemisahan berdasarkan berat jenis. Maka, mineral ikutan tersebut ikut tertangkap dalam kelompok sesuai dengan berat jenisnya.
Mineral Monazite, misalnya, sebuah mineral coklat kemerahan yang terdiri dari fosfat yang mengandung logam tanah jarang sebagai sumber cerium dan thorium. Mineral ini, menurut Fakhrizal mengandung radioaktif yang dapat dimanfaatkan untuk baterai mobil listrik.
“Kalau Monazite itu mengandung bahan radioaktif. Itukan bisa diproses untuk baterai mobil listrik, pesawat ruang angkasa. Itu bisa laku kan. Tapi siapa yang bikin pabriknya pengolahanya belum ada. Karena dijual bahan mentahnya kan tidak boleh juga,” katanya.
Kehadiran investor dengan teknologi terbarukan dipercaya Fakhrizal untuk menampung mineral-mineral ikutan tersebut. Jika hal ini diberlakukan, Fachrizal yakin akan membawa dampak baik bagi lingkungan karena limbah timah tidak terbuang sia-sia. Dia berharap, kelak masyarakat pun akan memiliki pekerjaan baru sebagai pencari mineral ikutan tersebut.
“Harusnya ini sudah terpikir,” kata Fachrizal. “Menggantikan timah dengan industri lain.”
Liputan oleh Fikri Muhammad ini didukung oleh program Journalism Fellowship “Build Back Better” yang diselenggarakan oleh The Society of Indonesian Environtmental Journalists(SIEJ) dan World Resources Institute (WRI) Indonesia. Liputan ini pertama kali terbit di National Geographic Indonesia pada tanggal 3 Desember 2020 dengan judul “Cerita kolong Timah Bangka di masa lalu sampai masa sekarang”.
- Dua dekade APSN, sampah masih jadi persoalan
 Universitas Pattimura (Unpatti) menegaskan pengelolaan sampah Indonesia masih pelik 20 tahun setelah Aksi Peduli Sampah Nasional dicanangkan.
Universitas Pattimura (Unpatti) menegaskan pengelolaan sampah Indonesia masih pelik 20 tahun setelah Aksi Peduli Sampah Nasional dicanangkan. - YLBHI: negara tampil inkompetensi dan gagal menghadapi bencana di Sumatera
 Di tengah kondisi ekologis yang rapuh, negara justru gagal menghadirkan sistem tanggap darurat yang memadai.
Di tengah kondisi ekologis yang rapuh, negara justru gagal menghadirkan sistem tanggap darurat yang memadai. - PLTMH swadaya di jantung rimba Kampung Silit
 Energi dari PLTMH adalah hadiah dari sungai yang terus mengalir karena hutannya dijaga dengan cinta dan hormat.
Energi dari PLTMH adalah hadiah dari sungai yang terus mengalir karena hutannya dijaga dengan cinta dan hormat. - Seruan pertobatan ekologis dari mimbar gereja hingga rimba Papua
 Pertobatan ekologis bukan sekadar ritual ibadah, melainkan perubahan radikal dalam cara pandang dan gaya hidup.
Pertobatan ekologis bukan sekadar ritual ibadah, melainkan perubahan radikal dalam cara pandang dan gaya hidup. - Napas terakhir TPA Cikundul Sukabumi dan inisiatif warga mengolah sampah
 Kisah TPA Cikundul Sukabumi hari ini adalah peringatan keras bahwa metode “kumpul-angkut-buang” telah usang.
Kisah TPA Cikundul Sukabumi hari ini adalah peringatan keras bahwa metode “kumpul-angkut-buang” telah usang. - 12 spesies tumbuhan endemik Indonesia berhasil diidentifikasi di tahun 2025
 Tumbuhan endemik itu terdiri atas 11 spesies dari famili Araceae dan satu spesies dari genus Syzygium (Myrtaceae).
Tumbuhan endemik itu terdiri atas 11 spesies dari famili Araceae dan satu spesies dari genus Syzygium (Myrtaceae).