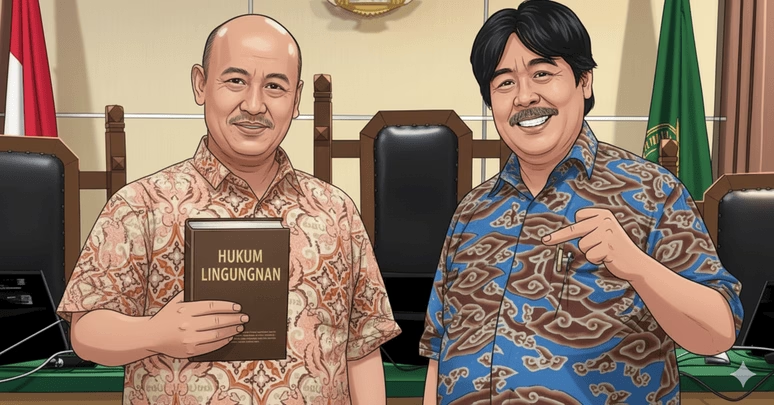Gas alam, khususnya metana yang menjadi komponen utamanya, memiliki potensi pemanasan global yang jauh lebih tinggi dari karbon dioksida.

Laporan terbaru berjudul “Transisi Palsu: Mengungkap Bahaya Gas Bumi dalam Transisi Energi Indonesia” yang disusun oleh Bhima Yudhistira Adhinegara, Shafa Kalila Aryanti, dan M. Bakhrul Fikri, serta diterbitkan oleh Greenpeace Indonesia dan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) pada 2025, menegaskan bahwa gas alam bukanlah solusi ramah lingkungan sebagaimana kerap dinarasikan. Sebaliknya, bahan bakar ini justru menjadi ancaman serius terhadap upaya menahan laju pemanasan global dan krisis iklim.
Dokumen tersebut memaparkan secara rinci bahwa gas alam, khususnya metana yang menjadi komponen utamanya, memiliki potensi pemanasan global yang jauh lebih tinggi dari karbon dioksida. Alih-alih mempercepat pencapaian target netral karbon Indonesia, ketergantungan pada gas bumi dinilai memperlambat transisi energi dan membahayakan masa depan lingkungan hidup.
Gas alam dan bahaya metana
Secara teknis, gas alam merupakan campuran hidrokarbon, terutama metana (CH₄) dan etana, yang selama ini dianggap sebagai bahan bakar “relatif bersih” karena emisi CO₂-nya lebih rendah dibanding batubara saat pembakaran. Namun, laporan Transisi Palsu menyoroti sisi lain dari gas alam yang kerap diabaikan: metana memiliki kemampuan memerangkap panas di atmosfer 82,5 kali lebih besar daripada karbon dioksida dalam rentang waktu 20 tahun.
Tingginya daya pemanasan global membuat metana menjadi ancaman utama dalam konteks pemanasan global. Laporan ini mencatat bahwa sebanyak 110 juta metrik ton metana diproduksi setiap tahun dari proses ekstraksi, transportasi, dan penggunaan bahan bakar fosil. Emisi ini berkontribusi besar terhadap percepatan perubahan iklim, terutama ketika terjadi kebocoran yang tidak terdeteksi atau tidak tertangani secara sistematis.
Karena itu, peralihan dari batubara ke gas alam sebagai strategi transisi dianggap sebagai langkah keliru. Emisi CO₂ dari pembakaran gas bumi memang lebih rendah, namun emisi metana yang menyertainya memiliki dampak pemanasan yang lebih besar dan jauh lebih berbahaya dalam jangka pendek.
Potensi emisi dari proyek PLTG dalam meningkatkan pemanasan global
Rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) di Indonesia menjadi salah satu sorotan utama dalam dokumen ini. Dalam skenario pembangunan PLTG sebesar 2,68 GW, laporan mencatat bahwa emisi karbon dioksida akan meningkat sebesar 5,97 juta ton per tahun, sedangkan emisi metana mencapai 5.332 ton per tahun.
Jika proyek PLTG diperluas hingga 22 GW sesuai target kebijakan energi nasional, maka emisi karbon dioksida melonjak menjadi 49,02 juta ton per tahun, sementara emisi metana bisa mencapai 43.768 ton per tahun. Peningkatan ini menunjukkan bahwa ekspansi PLTG justru akan memperparah krisis iklim, bukan mengatasinya.
Laporan ini menyimpulkan bahwa “transisi” yang bertumpu pada gas bumi adalah transisi palsu. Ketimbang mengurangi emisi secara signifikan, proyek-proyek PLTG justru menambah beban emisi gas rumah kaca di sektor energi.
Ancaman terhadap target net zero emission dan pemanasan global
Pemerintah Indonesia telah menetapkan target Net Zero Emission pada 2060. Namun, ketergantungan yang terus berlanjut terhadap gas bumi dinilai tidak sejalan dengan komitmen tersebut. Sebaliknya, laporan ini menilai bahwa ketergantungan terhadap gas bumi berisiko besar menggagalkan pencapaian target iklim nasional.
Gas bumi sering dipromosikan sebagai bahan bakar “jembatan” atau transisi sebelum beralih sepenuhnya ke energi terbarukan. Namun, dalam dokumen Transisi Palsu, Greenpeace dan CELIOS menyebut terminologi “transition fuel” sebagai bentuk penyesatan. Pasalnya, pembangunan infrastruktur gas seperti PLTG, jaringan pipa, dan terminal LNG akan mengikat Indonesia dalam penggunaan gas bumi selama puluhan tahun ke depan.
Investasi pada infrastruktur gas juga menyita ruang fiskal, mempersempit ruang untuk pengembangan energi bersih, dan meningkatkan risiko stranded asset—yakni infrastruktur energi yang dalam waktu dekat akan usang dan tak bernilai karena tuntutan dekarbonisasi global.
Sebagai tandingan dari gas bumi, dokumen ini menekankan bahwa energi terbarukan seperti surya dan angin mampu menurunkan emisi karbon sebesar 30–40 persen tanpa menimbulkan dampak sekunder seperti emisi metana. Energi terbarukan juga memiliki karakteristik produksi tanpa emisi langsung, sehingga lebih kompatibel dengan komitmen Paris Agreement.
Namun, laporan juga memperingatkan bahwa dominasi proyek-proyek PLTG dan infrastruktur gas bumi dalam dokumen perencanaan seperti RUPTL 2025–2034 dapat membajak ruang kebijakan dan investasi bagi energi bersih. Pemerintah justru berisiko gagal mencapai bauran energi terbarukan sebesar 75% pada tahun 2040 jika kecenderungan investasi ini terus dilanjutkan.
Gas bumi bukan solusi untuk mengurangi dampak pemanasan global
Melalui laporan “Transisi Palsu: Mengungkap Bahaya Gas Bumi dalam Transisi Energi Indonesia”, Greenpeace Indonesia dan CELIOS memberikan peringatan tegas terhadap arah kebijakan energi nasional. Bukti-bukti yang dikumpulkan menunjukkan bahwa gas bumi bukan solusi ramah iklim, melainkan sumber utama pemanasan global yang kian memperparah krisis iklim.
Dengan emisi metana yang tinggi, potensi pemanasan jangka pendek yang besar, dan kecenderungan pembangunan infrastruktur jangka panjang, gas bumi tidak selayaknya dijadikan tulang punggung transisi energi. Dokumen ini menyerukan kepada pemerintah untuk segera menghentikan perluasan proyek-proyek PLTG dan mengalihkan investasi ke energi terbarukan yang benar-benar bersih, adil, dan berkelanjutan.