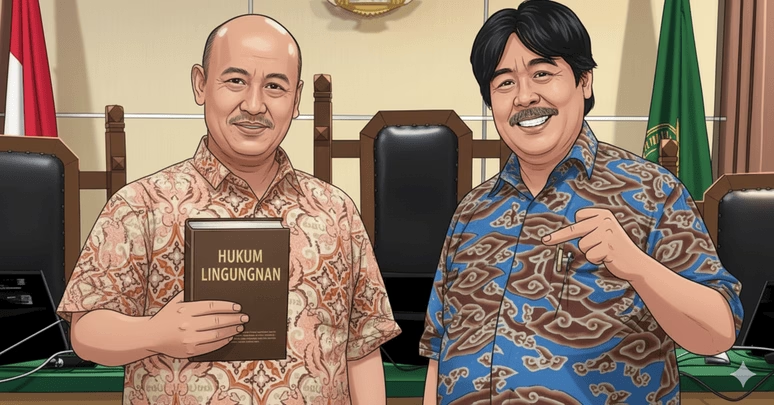COP30 akan menjadi momen penentuan: apakah narasi iklim Indonesia mampu meyakinkan dunia, atau justru akan terurai di bawah tekanan realitas?
Pada November 2025, mata dunia akan tertuju pada Belém, Brasil, kota yang dikenal sebagai “gerbang Amazon“. Di sinilah Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-30 (COP30) akan digelar, menjadi sebuah momen krusial dalam upaya global menahan laju krisis iklim. Konferensi ini bukan sekadar pertemuan rutin; ia adalah tenggat waktu bagi negara-negara untuk menyerahkan rencana iklim nasional yang baru dan lebih ambisius, yang dikenal sebagai Nationally Determined Contributions (NDCs), serta mengukur kemajuan nyata dalam komitmen pendanaan iklim yang telah lama dijanjikan.
Pemilihan Belém sebagai lokasi penyelenggaraan memiliki makna simbolis yang mendalam. Dengan latar belakang hutan hujan terbesar di dunia, isu pengelolaan hutan, solusi berbasis alam (nature-based solutions), dan hak-hak masyarakat adat secara otomatis akan menjadi sorotan utama. Dalam konteks ini, Indonesia, sebagai rumah bagi hutan tropis terbesar ketiga di dunia, akan menempati posisi sentral. Kehadiran Indonesia di panggung Amazon ini bukan hanya sebagai peserta, melainkan sebagai salah satu aktor kunci yang nasib komitmen iklimnya akan diuji di bawah sorotan global yang tajam.
Bagi Indonesia, COP30 adalah pertaruhan besar. Di satu sisi, pemerintah tengah giat mempersiapkan sebuah narasi nasional yang padu, terpoles, dan kuat, yang dirancang untuk menampilkan Indonesia sebagai pemimpin dalam aksi iklim dan ekonomi hijau. Namun di sisi lain, narasi ambisius ini berhadapan dengan tembok realitas yang kompleks: tantangan struktural yang mengakar, penilaian internasional yang kritis, serta jurang yang lebar antara kebijakan di atas kertas dan implementasi di lapangan.
Lokasi COP30 di Amazon menjadi pedang bermata dua bagi Indonesia. Ini adalah platform yang ideal untuk memamerkan kebijakan andalannya, Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030, dan memposisikan diri sebagai negara adidaya dalam solusi berbasis alam. Namun, panggung yang sama juga akan mengundang pengawasan paling ketat terhadap rekam jejak deforestasi dan kredibilitas kebijakan kehutanannya.
Potensi kemenangan dalam citra publik dapat dengan mudah berubah menjadi ujian akuntabilitas berisiko tinggi. Ketika perhatian dunia sudah terfokus pada hutan, narasi yang dibangun di Jakarta akan diuji secara langsung dengan bukti-bukti dari lapangan. Dengan demikian, COP30 akan menjadi momen penentuan: apakah narasi iklim Indonesia mampu meyakinkan dunia, atau justru akan terurai di bawah tekanan realitas?
Strategi diplomasi iklim Indonesia
Menghadapi panggung global yang menuntut di Belém, pemerintah Indonesia tidak datang tanpa persiapan. Sebuah strategi komunikasi dan diplomasi yang cermat tengah disusun untuk memastikan negara ini tampil dengan citra yang solid dan meyakinkan. Strategi ini bertumpu pada tiga pilar utama: pembangunan narasi tunggal yang terkonsolidasi, diplomasi finansial yang agresif untuk menuntut keadilan iklim, dan pembingkaian aksi iklim sebagai peluang ekonomi yang menguntungkan.
Upaya utama pemerintah adalah menyatukan suara dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan untuk menghindari pesan yang simpang siur di forum internasional. Yulia Suryanti, Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), mengartikulasikan pentingnya kesatuan ini. “Lucu kalau kita berdebat di luar negeri, tapi tidak satu suara di dalam negeri. Karena itu kami dorong pemahaman bersama dan penguatan kapasitas komunikasi, baik di pusat maupun daerah,” ujarnya dalam agenda Green Editor Forum yang digagas oleh SIEJ di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Pernyataan ini menggarisbawahi pendekatan dari atas ke bawah untuk memastikan semua delegasi dan perwakilan Indonesia menyampaikan pesan yang seragam dan selaras dengan agenda nasional.
Bagian penting dari strategi ini adalah penyederhanaan informasi. Isu perubahan iklim sering kali terperangkap dalam jargon teknis yang sulit dipahami publik. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah berupaya menerjemahkan kompleksitas tersebut ke dalam bahasa yang lebih mudah dicerna.
“Kami sedang berupaya menyederhanakan penyampaian informasi, agar tidak terjadi salah persepsi. Isu perubahan iklim ini sangat teknikal, jadi penting memastikan publik dan pemangku kepentingan memahami dengan benar,” tambah Yulia.
Diplomasi finansial dan perdagangan karbon
Di arena diplomasi, prioritas utama Indonesia adalah isu pendanaan iklim. Delegasi Indonesia akan secara tegas menuntut negara-negara maju untuk memenuhi janji mereka yang telah lama tertunda, terutama komitmen untuk menyediakan pendanaan sebesar 100 miliar USD per tahun yang berasal dari Copenhagen Accord.
Janji ini, menurut laporan resmi UNFCCC, masih jauh dari realisasi. Lebih jauh lagi, target baru sebesar 1,3 triliun USD dalam New Collective Quantified Goals baru disepakati untuk direalisasikan sebesar 300 miliar USD, menyisakan celah pendanaan yang sangat besar.
Sikap Indonesia dalam hal ini dibingkai sebagai perjuangan untuk keadilan global. Seperti dilansir TanahAir.Net, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, menyatakan bahwa negara-negara berkembang membutuhkan “bukti nyata, bukan hanya janji-janji”. Dengan mengambil posisi ofensif dalam isu ini, Indonesia secara strategis menempatkan dirinya sebagai pemimpin suara dari negara-negara Selatan (Global South).
Ini adalah langkah diplomasi yang cerdas, karena dengan menyoroti kegagalan negara-negara maju memenuhi komitmen finansial mereka, Indonesia dapat secara pre-emptif menangkis kritik terhadap kekurangan kebijakan domestiknya sendiri. Taktik ini mengalihkan fokus dari kegagalan implementasi di dalam negeri ke tanggung jawab historis dan janji yang diingkari oleh negara-negara Utara, sebuah manuver yang efektif untuk membangun solidaritas di antara negara-negara berkembang.
Lebih dari sekadar menuntut dana, Indonesia juga melihat peluang bisnis. Paviliun Indonesia di COP30 dirancang tidak hanya sebagai ruang seminar, tetapi sebagai pusat “diplomasi karbon” yang aktif untuk memperluas kerja sama perdagangan karbon. Beberapa kesepakatan potensial yang sedang dijajaki termasuk rencana Norwegia untuk membeli 12 juta ton CO₂ ekuivalen pada tahun 2035, serta potensi kolaborasi dengan Jepang dan Korea. Indonesia juga mendorong perjanjian pengakuan bersama (Mutual Recognition Agreements/MRAs) dengan standar karbon global seperti Verra dan Gold Standard untuk memuluskan jalan bagi kredit karbonnya di pasar internasional.
Pilar ketiga dari strategi Indonesia adalah mengubah persepsi tentang aksi iklim dari beban menjadi peluang. Pemerintah secara aktif mempromosikan gagasan bahwa transisi hijau adalah jalan menuju pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi baru.
Yulia Suryanti dari KLH menegaskan visi ini. “COP30 bukan hanya forum negosiasi, tapi juga ajang menunjukkan bahwa isu iklim bisa menjadi peluang pembangunan berkelanjutan. Kami ingin memperlihatkan bahwa Indonesia mampu memanfaatkannya untuk mendorong ekonomi hijau,” paparnya.
Narasi ini diwujudkan melalui “Kebijakan Industri Hijau” (Green Industrial Policy) yang akan dipamerkan di COP30. Pemerintah akan menyajikan 14 proyek pengurangan emisi sebagai bagian dari “portofolio iklim” yang dirancang untuk menarik investasi internasional. Pendekatan ini menunjukkan pergeseran paradigma yang jelas: komitmen iklim tidak lagi hanya dilihat sebagai kewajiban lingkungan, tetapi sebagai aset ekonomi yang dapat diperdagangkan.
Dengan mengemas janji-janji iklimnya sebagai peluang investasi yang menarik, Indonesia berharap dapat menarik modal yang dibutuhkan untuk mendanai transisinya. Namun, strategi monetisasi ini juga membawa risiko. Jika motivasi utamanya adalah keuntungan finansial, ada kekhawatiran bahwa prioritas akan diberikan pada proyek-proyek yang terlihat bagus di atas kertas dan menghasilkan kredit karbon yang mudah dijual, bukan pada proyek-proyek yang memberikan pengurangan emisi yang paling substansial, berkelanjutan, dan berkeadilan.
Tantangan kredibilitas dan keadilan iklim
Di balik narasi resmi pemerintah yang terstruktur rapi, muncul suara-suara kritis dari masyarakat sipil domestik dan analis internasional. Mereka tidak hanya mempertanyakan angka-angka dan target, tetapi juga fondasi keadilan dan integritas dari kebijakan iklim Indonesia. Kritik-kritik ini menghadirkan sebuah narasi tandingan yang kuat, yang menantang kredibilitas komitmen Indonesia menjelang COP30.
Bagi banyak organisasi masyarakat sipil di Indonesia, krisis iklim bukanlah sekadar masalah teknis tentang ton emisi karbon, melainkan isu struktural yang berakar pada ketidakadilan. Torry Kuswardono dari Yayasan Pikul menyuarakan perspektif ini dengan tajam. “Krisis iklim adalah persoalan struktural. Kalau akar ketimpangan tidak diatasi, kebijakan iklim hanya akan melahirkan ketidakadilan baru,” katanya pada Green Editor Forum yang digagas oleh SIEJ di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Pernyataan ini menyoroti kekhawatiran mendalam bahwa kebijakan iklim yang dirancang dari atas ke bawah, tanpa partisipasi publik yang bermakna, berisiko mengorbankan hak-hak masyarakat lokal dan adat demi mencapai target nasional.
Kekhawatiran ini diperkuat oleh tuntutan agar kebijakan iklim tidak hanya selaras dengan perjanjian internasional, tetapi juga dengan konstitusi negara yang menjamin hak-hak warga negara. “Kami ingin negara setia pada konstitusi, bukan hanya pada target iklim di atas kertas,” tegas Torry.
Ini adalah seruan untuk memastikan bahwa transisi hijau tidak menjadi dalih untuk perampasan tanah, penggusuran, atau marginalisasi komunitas yang paling rentan, yang justru sering kali menjadi penjaga ekosistem.
Kritik tidak hanya datang dari dalam negeri. Lembaga analisis ilmiah independen, Climate Action Tracker (CAT), secara konsisten memberikan rapor merah untuk aksi iklim Indonesia. Peringkat keseluruhan kebijakan dan tindakan Indonesia adalah “Sangat Tidak Cukup” (Critically Insufficient). Peringkat ini memiliki implikasi yang serius: jika semua negara di dunia mengikuti pendekatan Indonesia, pemanasan global akan melampaui 4°C, sebuah skenario bencana.
CAT menyoroti beberapa kelemahan fundamental. Pertama, target NDC Indonesia dinilai tidak ambisius karena dapat dicapai dengan kebijakan yang sudah ada, yang berarti komitmen tersebut tidak mendorong aksi iklim tambahan yang signifikan. Kedua, target tersebut gagal mengatasi emisi dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara off-grid atau captive, yang jumlahnya terus bertambah untuk melayani industri. Ketiga, ketergantungan yang sangat besar pada sektor FOLU untuk mencapai target NDC dianggap sangat berisiko.
Terdapat jurang yang menganga antara target serapan bersih -140 MtCO2e dan proyeksi emisi saat ini dari sektor lahan yang diperkirakan masih mencapai sekitar 920 MtCO2e per tahun pada 2030. Menutup kesenjangan sebesar itu dalam waktu kurang dari satu dekade dianggap sangat tidak mungkin tanpa perubahan kebijakan yang radikal.
Menariknya, kritik dari masyarakat sipil lokal dan analis internasional, meskipun datang dari sudut pandang yang berbeda, bertemu pada satu titik temu: kurangnya integritas dan keadilan dalam kerangka kebijakan iklim Indonesia saat ini. Seruan lokal untuk keadilan sosial dan pengakuan hak-hak masyarakat adat bergema dalam analisis internasional yang menyoroti kegagalan dalam merancang transisi yang adil dan ambisius. Keduanya sama-sama menuntut pergeseran kebijakan yang lebih mendasar, yang tidak hanya berfokus pada angka di atas kertas, tetapi juga pada keadilan bagi manusia dan kelestarian ekosistem.
Antara komitmen dan implementasi
Jurang antara janji dan kenyataan semakin terlihat jelas ketika menelaah implementasi kebijakan di sektor-sektor kunci. Di balik komitmen hijau yang digaungkan di forum internasional, Indonesia masih bergulat dengan paradoks yang mendalam, terutama dalam transisi energi dan praktik penggunaan lahan. Kontradiksi ini menunjukkan adanya ketergantungan jalur (path dependency) pada ekonomi ekstraktif yang sulit dilepaskan, yang pada akhirnya merusak kredibilitas narasi iklimnya.
Kemitraan Transisi Energi yang Adil (Just Energy Transition Partnership/JETP) diluncurkan dengan gegap gempita sebagai tonggak kerja sama iklim internasional. Dengan janji pendanaan sebesar 20 miliar USD, JETP bertujuan untuk mengakselerasi pensiun dini PLTU batubara dan meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi. Namun, implementasinya berjalan lambat. Pencairan dana yang dijanjikan masih sangat minim, dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) yang krusial terus tertunda akibat perdebatan sengit di parlemen.
Paradoks terbesar terletak pada kebijakan batubara. Sementara pemerintah merencanakan pensiun dini beberapa PLTU, pada saat yang sama, sekitar 40 PLTU baru masih dalam tahap konstruksi. Sebagian besar adalah PLTU captive (pembangkit di luar jaringan PLN untuk kebutuhan industri) yang bahkan tidak tercakup dalam target utama JETP, menciptakan celah emisi yang signifikan. Akibatnya, batubara masih mendominasi sekitar 70% dari bauran listrik nasional.
Situasi ini diperparah oleh RUU EBET yang kontroversial, yang memasukkan sumber “energi baru” seperti produk turunan batubara (gasifikasi dan likuifaksi), sebuah langkah yang dinilai banyak pihak justru akan melanggengkan ketergantungan pada bahan bakar fosil, bukan mengakhirinya.
Kondisi ini menunjukkan adanya ketergantungan jalur yang kuat pada batubara, yang bukan hanya sumber energi tetapi juga komoditas ekspor terbesar dan sumber pendapatan negara yang signifikan. Kepentingan politik dan ekonomi yang mengakar di sektor ini menciptakan hambatan struktural yang membuat transisi energi berjalan sangat lambat. Kebijakan yang tampak kontradiktif bukanlah sebuah kebetulan, melainkan cerminan dari realitas politik di mana pemerintah enggan atau tidak mampu menantang status quo yang diuntungkan oleh industri fosil.
Di sektor lahan, kontradiksi serupa juga terjadi. Kritik terhadap kebijakan FOLU Net Sink yang mengizinkan “deforestasi terencana” terkonfirmasi oleh berbagai proyek pembangunan skala besar yang terus berjalan. Program lumbung pangan (Food Estate), yang bertujuan mengubah jutaan hektar lahan menjadi kawasan pertanian, berisiko menyebabkan deforestasi besar-besaran, terutama di wilayah hutan yang masih tersisa.
Selain itu, kebijakan mandatori biodiesel (B35 yang akan ditingkatkan menjadi B40/B50) juga menciptakan dilema. Di satu sisi, kebijakan ini dipromosikan sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan pada solar fosil. Di sisi lain, ia mendorong ekspansi perkebunan kelapa sawit, yang secara historis menjadi salah satu pendorong utama deforestasi di Indonesia.
Ini adalah contoh klasik bagaimana satu kebijakan “hijau” dapat memicu dampak negatif di sektor lain. Bahkan, pemerintahan baru telah mengisyaratkan rencana untuk membuka 20 juta hektar lahan hutan lagi untuk proyek pangan dan energi, sebuah sinyal kuat bahwa model pembangunan yang berbasis pada konversi hutan akan terus berlanjut.
Pola ini mengindikasikan adanya strategi “permainan cangkang karbon” (carbon shell game). Pemerintah tampaknya sangat mengandalkan angka serapan karbon yang besar (meskipun diperdebatkan) dari sektor FOLU untuk menciptakan “ruang” dalam anggaran karbon nasional. Ruang ini kemudian digunakan untuk membenarkan transisi energi yang lebih lambat dan kelanjutan proyek-proyek ekstraktif yang menghasilkan emisi tinggi.
Dengan kata lain, klaim penyerapan karbon di sektor hutan digunakan untuk menutupi kelambanan aksi di sektor energi dan industri. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk mencapai target NDC di atas kertas tanpa harus membuat keputusan-keputusan sulit yang dapat mengganggu kepentingan ekonomi dan politik yang sudah mapan.
Indonesia akan tiba di Belém dengan sebuah narasi yang telah dirancang dengan cermat: sebuah kisah tentang persatuan nasional, peluang ekonomi hijau, dan ambisi iklim yang tinggi. Namun, narasi ini akan dihadapkan pada ujian kredibilitas yang paling berat. Di panggung global yang berlokasi di jantung Amazon, di mana isu hutan menjadi pusat perhatian, janji-janji akan ditimbang dengan bukti-bukti, dan retorika akan diadu dengan realitas.
Konflik inti yang telah diuraikan dalam laporan ini adalah pertentangan antara narasi resmi dan kenyataan di lapangan. Di satu sisi, ada klaim kepemimpinan iklim. Di sisi lain, ada realitas ketergantungan pada batubara, kebijakan kehutanan yang dikritik karena melegalkan deforestasi, target yang dinilai “sangat tidak cukup” oleh analisis ilmiah, dan suara-suara masyarakat sipil yang menuntut keadilan iklim yang sering kali terabaikan.
COP30 di Belém akan menjadi momen di mana fokus dunia bergeser dari sekadar janji ke implementasi dan akuntabilitas. Para mitra internasional, investor, dan masyarakat sipil global semakin waspada terhadap pengumuman ambisius yang tidak diikuti dengan langkah-langkah nyata yang dapat diverifikasi. Dalam konteks ini, peran media dan transparansi menjadi sangat krusial.
Seperti yang diungkapkan oleh Joni Aswira Putra, Ketua Umum Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ). “Editor memegang peran penting memastikan itu terjadi di ruang redaksi. Kolaborasi antara media, pemerintah, dan masyarakat sipil menjadi kunci, agar pemberitaan mengenai komitmen iklim Indonesia semakin transparan dan berdampak,” katanya.
Pada akhirnya, Indonesia berada di persimpangan jalan. Negara ini memiliki peluang unik untuk menunjukkan kepada dunia bagaimana sebuah negara berkembang yang besar dapat menyelaraskan kebijakan industrinya dengan tujuan iklim global. Namun, keberhasilan di Belém tidak akan diukur dari kemegahan paviliunnya atau jumlah kesepakatan dagang karbon yang ditandatangani.
Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah apakah Indonesia dapat menerjemahkan komitmen-komitmennya menjadi pengurangan emisi yang nyata, terukur, adil, dan berkelanjutan di lapangan. Di bawah mikroskop global yang terpasang di Amazon, tidak akan ada tempat untuk bersembunyi. Kredibilitas narasi iklim Indonesia akan dipertaruhkan.
- COP30 Brasil, antara kemajuan nyata dan janji yang mengambang
- Belém Mutirão dan paradoks diplomasi Indonesia di Amazon
- Ketika iman menggugat keadilan iklim di tengah kepungan lobi fosil
- Indonesia di panggung COP30: aktif kritik teks, pasif aksi iklim
- Antara “Supermarket” karbon dan jerat utang iklim
- Ambisi SNDC Indonesia terjebak ekspansi ekstraktif, mengancam gambut dan laut