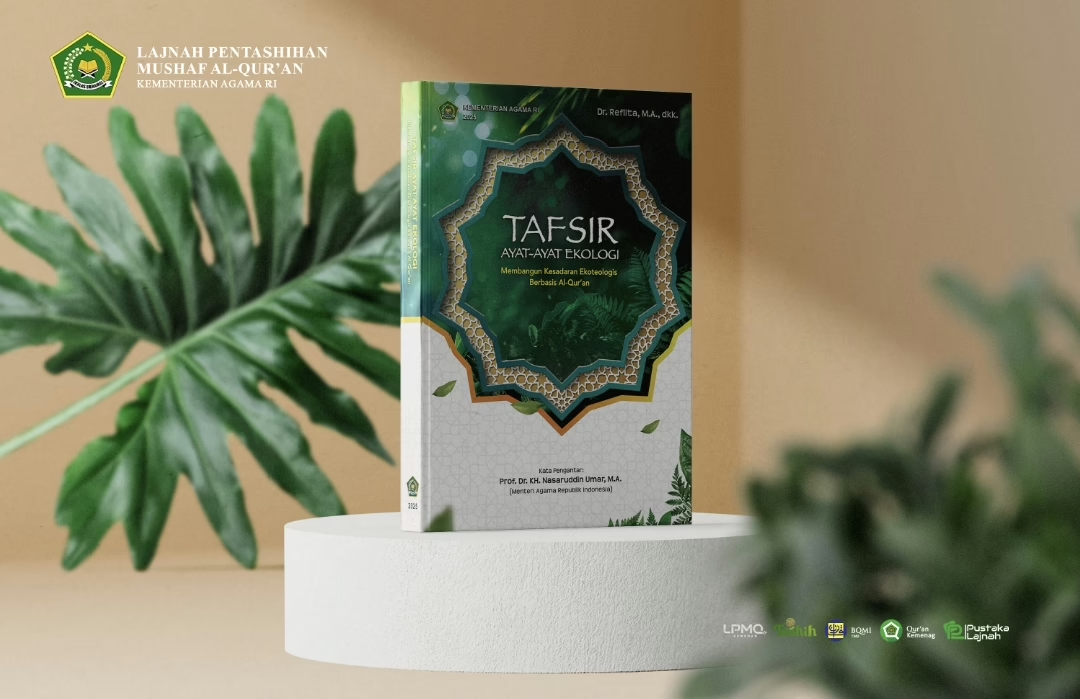Di tengah hiruk pikuk Jakarta, sebuah peristiwa simbolis berlangsung di Gedung Bayt Al-Qur’an dan Museum Istiqlal (BQMI) pada Senin, 6 Oktober 2025. Di tempat yang didedikasikan untuk merawat firman Tuhan dalam bentuk mushaf, Kementerian Agama (Kemenag) meluncurkan sebuah ikhtiar untuk membaca firman-Nya yang terhampar di alam semesta. Menteri Agama Nasaruddin Umar secara resmi merilis buku “Tafsir Ayat-Ayat Ekologi: Membangun Kesadaran Ekoteologis Berbasis Al-Qur’an”.
Dalam sambutannya, Menag Nasaruddin Umar menggemakan sebuah metafora kuat yang menjadi jantung dari karya ini. “Jika Al-Qur’an merupakan kumpulan ayat mikrokosmos, maka alam semesta ini adalah kumpulan ayat makrokosmos. Keduanya sama-sama ayat Allah,” ujarnya.
Sebuah penegasan bahwa alam bukanlah entitas mati yang bisa dieksploitasi, melainkan sebuah kitab suci yang terbuka, yang menuntut untuk dibaca dengan penuh takzim dan tanggung jawab.
Namun, visi sakral ini berhadapan langsung dengan kontras yang brutal di lapangan. Buku yang disusun oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMQ) ini sendiri dibuka dengan data yang mengkhawatirkan: Indonesia kehilangan lebih dari 175,4 ribu hektar hutan pada tahun 2024 saja, menempatkan negara ini sebagai salah satu negara dengan laju kehilangan hutan tercepat di dunia. Hutan yang disebut sebagai paru-paru dunia, rumah bagi 17% spesies flora dan fauna global, kini terengah-engah.
Peluncuran buku ini, oleh karenanya, bukan sekadar seremoni penerbitan biasa. Ini adalah sebuah manuver strategis dari negara. Ketika lembaga negara tertinggi dalam urusan Al-Qur’an, dengan restu langsung dari Menteri Agama, merilis sebuah tafsir ekologi, ini menandakan pergeseran paradigma. Isu lingkungan tidak lagi hanya domain aktivis, ilmuwan, atau politisi, tetapi secara resmi dibingkai sebagai panggilan moral dan keagamaan yang mendesak bagi mayoritas penduduk Indonesia.
Terlebih lagi, inisiatif ini secara eksplisit diselaraskan dengan program prioritas pemerintah, “Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka,” yang salah satu butirnya adalah memperkuat kehidupan harmonis dengan lingkungan.
Ini adalah sebuah sinyal bahwa negara berupaya memobilisasi sentimen dan infrastruktur keagamaan—mulai dari kurikulum pesantren, khotbah Jumat, hingga organisasi massa Islam—sebagai garda terdepan dalam kebijakan lingkungan nasional.
Buku Tafsir Ayat-Ayat Ekologi mengajukan sebuah diagnosis radikal: krisis lingkungan yang kita hadapi pada dasarnya bukanlah krisis teknologi atau kebijakan, melainkan krisis spiritual. “Kerusakan alam sejatinya adalah refleksi dari krisis hubungan manusia dengan dirinya, sesama, dan alam sekitarnya,” demikian tertulis dalam pendahuluannya.
Ketika manusia memisahkan relasinya dengan alam dari relasi keimanannya dengan Tuhan, maka alam kehilangan nilai sakralnya dan menjadi objek eksploitasi semata.
Untuk menyembuhkan luka ini, buku ini menawarkan jembatan bernama “Ekoteologi”—sebuah pendekatan integratif yang menyatukan kembali teologi (ilmu tentang Tuhan, logos) dengan rumah kita bersama, Bumi (oikos). Pendekatan ini berupaya memulihkan pandangan sakral terhadap alam, sebuah gagasan yang sejalan dengan kritik mendalam dari pemikir Islam global, Seyyed Hossein Nasr. Sebagaimana disinggung dalam buku ini dan ulasan Kemenag, Nasr dalam karyanya Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man berargumen bahwa modernitas telah mencabut sakralitas alam dari kesadaran manusia.
Akar masalahnya, menurut buku ini, adalah dominasi paradigma antroposentrisme yang menempatkan manusia sebagai “penguasa tunggal atas alam”. Pandangan ini, yang diperparah oleh apa yang disebut Menteri Agama sebagai “teologi kita yang terlalu maskulin,” telah melahirkan hubungan yang dominatif dan eksploitatif, bukan pengasuhan dan pemeliharaan.
Dengan membingkai ulang diagnosis masalah dari material menjadi spiritual, pendekatan yang ditawarkan pun berubah secara fundamental. Solusinya bukan lagi sekadar pajak karbon, teknologi hijau, atau regulasi pemerintah semata. Solusi yang ditawarkan adalah transformasi batin, sebuah pertobatan (taubah) kolektif, dan perubahan cara pandang dunia. Ini secara efektif menempatkan para ulama, dai, dan institusi keagamaan di garis depan pertempuran iklim, bukan sebagai aktor pendukung, tetapi sebagai penyembuh esensial bagi jiwa kolektif bangsa yang terluka.
Tafsir hijau untuk konsep kunci Islam
Inti dari buku Tafsir Ayat-Ayat Ekologi adalah sebuah proyek teologis yang canggih: menafsirkan ulang konsep-konsep kunci dalam Al-Qur’an melalui lensa ekologis, mengubahnya dari ajaran abstrak menjadi pedoman etis yang konkret untuk berinteraksi dengan alam.
Pertama, konsep Rabb al-‘Ālamīn (Tuhan Pemelihara Semesta Alam) dalam Surah Al-Fatihah/1:2. Tuhan tidak lagi dipahami hanya sebagai Pencipta yang transenden dan jauh, tetapi sebagai Rabb—Pengasuh aktif yang secara terus-menerus memelihara setiap jaring ekosistem, dari rotasi bumi hingga rantai makanan. Dengan demikian, merusak alam, seperti menggunduli hutan atau mencemari sungai, pada hakikatnya adalah sebuah tindakan pengingkaran terhadap sifat rububiyyah (pemeliharaan) Allah.
Kedua, peran manusia sebagai khalifah (khalifah) di bumi, sebagaimana termaktub dalam Surah Al-Baqarah/2:30, ditegaskan kembali bukan sebagai penguasa absolut, melainkan sebagai pemelihara dan pengelola yang bertanggung jawab. Kekhawatiran para malaikat bahwa manusia akan “membuat kerusakan… dan menumpahkan darah” disajikan sebagai peringatan abadi terhadap potensi destruktif manusia jika amanah ini disalahgunakan.
Ketiga, istilah Al-Qur’an untuk kerusakan, fasād fi al-ard (kerusakan di muka bumi), secara eksplisit dihubungkan dengan degradasi lingkungan modern. Mengacu pada Surah Ar-Rūm/30:41, “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia,” buku ini membingkai polusi, deforestasi, dan perubahan iklim sebagai manifestasi nyata dari dosa ekologis.
Keempat, konsep amanah (amanah) dari Surah Al-Ahzāb/33:72 —sebuah tanggung jawab kosmik yang begitu berat hingga langit, bumi, dan gunung menolaknya— dihubungkan langsung dengan kecenderungan manusia untuk berbuat zalim (ẓalūm) dan bodoh (jahūl). Sifat inilah yang termanifestasi dalam kerakusan dan kecerobohan ekologis.
Buku ini secara sistematis membangun argumen bahwa amanah ini berfungsi sebagai pagar etis yang membatasi konsep taskhīr (penundukan alam). Sebagaimana ditegaskan oleh Menag, taskhīr bukanlah “cek kosong” untuk eksploitasi yang didorong oleh ketamakan, melainkan “izin terbatas” untuk kemanfaatan bersama. Dengan menyandingkan taskhīr dengan amanah, buku ini membangun sebuah kerangka teologis yang koheren dan kuat, yang menolak interpretasi eksploitatif terhadap ajaran agama.
Untuk memperjelas pergeseran makna ini, berikut adalah rangkumannya:
| Konsep Kunci | Makna Konvensional | Tafsir Ekologis (Menurut Buku) | Ayat Rujukan Utama |
| Khalifah | Pengganti, Pemimpin | Pemelihara & Penjaga Etis Ekosistem | Al-Baqarah/2:30 |
| Amanah | Kepercayaan, Titipan | Tanggung Jawab Kosmik Merawat Ciptaan | Al-Ahzāb/33:72 |
| Fasād | Kerusakan Moral/Sosial | Kerusakan Ekologis (Polusi, Deforestasi) | Ar-Rūm/30:41 |
| Mīzān | Timbangan, Keadilan | Keseimbangan Ekosistem Ilahi | Ar-Raḥmān/55:7-9 |
| Taskhīr | Penundukan, Penaklukan | Izin Terbatas untuk Manfaat, Bukan Eksploitasi Rakus | Al-Jāṡiyah/45:13 |
Menanam pohon sebagai bentuk dzikir
Tafsir ini tidak berhenti di ranah wacana. Ia mengalir deras menuju praksis, mentransformasi tindakan-tindakan ekologis menjadi laku ibadah yang bernilai spiritual. Puncak dari etika lingkungan Islam ini terangkum dalam sebuah hadis yang dikutip dalam pendahuluan buku: “Jika kiamat terjadi dan di tangan salah seorang dari kalian ada sebatang bibit pohon (kurma), maka jika ia masih mampu… hendaklah ia menanamnya”.
Ini adalah sebuah perintah etis yang radikal. Tindakan menanam pohon di ambang kiamat adalah sebuah aksi yang sepenuhnya terlepas dari kalkulasi untung-rugi duniawi. Ia adalah wujud kepasrahan murni pada perintah ilahi untuk merawat kehidupan, sebuah ekspresi harapan tertinggi di tengah keputusasaan. Inilah yang dimaksud ketika spiritualitas Islam diajak meluas dari sajadah ke hutan, dari ruang ibadah personal ke ruang publik ekologis.
Dengan membingkai aksi nyata seperti menanam pohon, menjaga kebersihan air, dan mengurangi sampah sebagai bagian dari ibadah, buku ini secara fundamental mendemokratisasi gerakan lingkungan. Tanggung jawab ekologis tidak lagi menjadi beban eksklusif bagi para aktivis, ilmuwan, atau pembuat kebijakan. Ia menjadi panggilan jiwa bagi setiap Muslim dalam praktik spiritualitas sehari-hari.
Seseorang mungkin merasa tidak berdaya mengubah kebijakan nasional, tetapi ia memiliki kuasa penuh untuk menanam pohon di halaman rumahnya atau memungut sampah di lingkungannya sebagai sebuah bentuk dzikir dan pengakuan akan Tuhan sebagai Rabb al-‘Ālamīn. Ini adalah sebuah strategi yang berpotensi melepaskan gelombang partisipasi massa yang berakar pada kesalehan personal—sebuah kekuatan yang jauh lebih dahsyat di tengah masyarakat Indonesia dibandingkan seruan-seruan sekuler semata.
Pada akhirnya, sebuah pertanyaan besar tetap menggantung: mampukah sebuah buku tafsir, sekalipun didukung penuh oleh negara, mengubah arah kerusakan lingkungan yang telah digerakkan oleh mesin ekonomi dan politik yang begitu perkasa?
Tentu saja, menata ulang teologi bukanlah solusi tunggal. Namun, ia adalah langkah pertama yang paling fundamental dan tak terhindarkan. Kebijakan dan teknologi secanggih apa pun akan rapuh jika tidak ditopang oleh pergeseran kesadaran dan sistem nilai di tingkat kolektif. Buku Tafsir Ayat-Ayat Ekologi adalah sebuah ikhtiar serius untuk memantik pergeseran itu dari jantung identitas budaya dan spiritual bangsa Indonesia.
Ia mengajak kita kembali membaca “kitab alam” yang terhampar luas. Setelah berpuluh-puluh tahun kita merobek halaman-halamannya dan mengabaikan peringatan-peringatannya, pertanyaan yang tersisa kini adalah: bersediakah kita belajar membacanya kembali, bukan dengan mata seorang penakluk, tetapi dengan hati seorang khalifah?
- Kecemasan Publik terhadap Rencana Pembangunan PLTN
- Labirin Lumpur di Perbukitan Kapur Jampang
- Matinya Macan Tutul Jawa Penjaga Rimba Sanggabuana
- Gunung Slamet Tergerus, Banjir Melanda Lembah
- Perlawanan Sunyi di Jantung Hutan Bengkulu
- Tambang batu bara ganggu kehidupan Gajah Sumatera