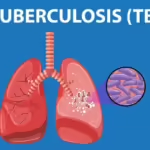Anak muda Indonesia semakin mengadopsi gaya hidup ramah lingkungan, didorong oleh kesadaran akan krisis iklim dan pengaruh media sosial, mengubah kepedulian terhadap bumi menjadi praktik keren sehari-hari seperti thrifting dan zero waste.
Pernah nggak sih, kamu merasa resah lihat tumpukan sampah plastik di sudut kota, atau khawatir soal perubahan iklim yang makin terasa dampaknya? Tenang, kamu nggak sendirian! Di tengah hiruk pikuk kehidupan modern, ada sebuah pergeseran menarik yang sedang terjadi di kalangan anak muda Indonesia. Dulu, mungkin slogan “YOLO” (You Only Live Once) yang identik dengan gaya hidup serba cepat dan konsumtif begitu menggema. Tapi kini, angin perubahan mulai berhembus. Semakin banyak Generasi Z dan Milenial yang sadar bahwa bumi ini cuma satu, dan masa depan kita bergantung padanya.
Kesadaran ini bukan lagi sekadar obrolan warung kopi atau tagar di media sosial. Gaya hidup ramah lingkungan, atau sustainable living, kini menjelma menjadi sebuah gerakan nyata yang diadopsi oleh anak muda Indonesia. Mereka melihat langsung dampak kerusakan lingkungan—mulai dari kualitas udara yang menurun hingga krisis air bersih—dan menyadari bahwa generasi merekalah yang akan menanggung akibat terbesar jika tidak ada perubahan. Ini bukan lagi sekadar tren sesaat, melainkan sebuah pilihan sadar yang menjadi bagian penting dari identitas dan gaya hidup mereka.
Kami akan mengajakmu menyelami dunia gaya hidup hijau ala anak muda Indonesia: apa saja tren yang sedang hits, siapa sosok inspiratif di baliknya, apa motivasi mereka, tantangan apa yang dihadapi, dan bagaimana kamu juga bisa ikut ambil bagian dalam gerakan keren ini.
Tren hijau yang lagi hits
Lupakan kesan kuno atau ribet. Gaya hidup ramah lingkungan di tangan anak muda Indonesia justru tampil stylish, kreatif, dan penuh semangat. Mereka berhasil mengubah kepedulian terhadap bumi menjadi serangkaian praktik sehari-hari yang tidak hanya berdampak positif, tapi juga dianggap keren dan relevan dengan zaman. Ini bukan lagi soal pengorbanan, tapi tentang pilihan cerdas untuk hidup yang lebih baik dan seimbang.
Gerakan sustainable living atau gaya hidup berkelanjutan kini semakin marak. Bagi sebagian anak muda, ini adalah kewajiban moral, sementara bagi yang lain, ini adalah lifestyle keren yang patut diikuti. Data menunjukkan tren positif ini; survei mencatat bahwa mayoritas masyarakat Indonesia pernah membeli produk ramah lingkungan, dengan Generasi Z menjadi kelompok yang dominan dalam penggunaannya. Ini menandakan bahwa keberlanjutan mulai merasuk ke berbagai aspek kehidupan, mulai dari pilihan produk sehari-hari hingga cara mereka berinteraksi dengan lingkungan.
Salah satu bintang utama dalam tren ini adalah Zero Waste Lifestyle atau gaya hidup minim sampah. Konsep ini mendorong kita untuk mengurangi produksi sampah seminimal mungkin, bahkan hingga nol, melalui prinsip 5R: Refuse (menolak yang tidak perlu), Reduce (mengurangi konsumsi), Reuse (menggunakan kembali), Recycle (mendaur ulang), dan Rot (mengomposkan sampah organik). Praktik nyata yang sering terlihat adalah kebiasaan membawa tas belanja kain sendiri, menggunakan botol minum isi ulang (tumbler), membawa wadah makanan sendiri, dan menolak penggunaan plastik sekali pakai seperti sedotan atau kantong kresek. Upaya ini didorong oleh kesadaran akan bahaya sampah plastik yang sulit terurai dan mencemari lingkungan, terutama lautan Indonesia yang kaya.
Di ranah fashion, Thrifting atau berburu pakaian bekas menjadi fenomena besar. Jauh dari kesan kumuh, thrifting kini digandrungi karena menawarkan gaya unik, vintage, dan anti-mainstream dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan membeli baju baru. Sensasi “berburu harta karun” di tumpukan baju bekas memberikan kepuasan tersendiri. Lebih dari sekadar gaya dan hemat, thrifting adalah bentuk perlawanan terhadap industri fast fashion yang boros sumber daya dan menghasilkan banyak limbah tekstil. Dengan membeli barang bekas, anak muda turut memperpanjang usia pakai pakaian dan mengurangi dampak negatif produksi baru.
Secara umum, Mengurangi Sampah Plastik menjadi fokus utama. Selain membawa peralatan makan dan minum sendiri, anak muda juga mulai lebih selektif memilih produk dengan kemasan minimal atau yang mudah didaur ulang. Beberapa bahkan mulai melirik sistem isi ulang (refill) untuk produk kebutuhan sehari-hari seperti sabun atau deterjen, meskipun akses ke toko refill atau bulk store masih menjadi tantangan di beberapa tempat. Kesadaran akan volume sampah plastik yang masif di Indonesia menjadi pendorong kuat di balik gerakan ini.
Perubahan juga terlihat dalam mobilitas. Transportasi Hijau semakin diminati. Banyak anak muda yang mulai beralih menggunakan transportasi umum, bersepeda, atau berjalan kaki untuk aktivitas sehari-hari, terutama di perkotaan. Survei menunjukkan bahwa lebih dari separuh anak muda menggunakan transportasi umum beberapa kali dalam seminggu. Pilihan ini tidak hanya mengurangi emisi karbon dari kendaraan pribadi tetapi juga seringkali lebih efisien dan menyehatkan.
Pemilihan Produk Ramah Lingkungan dalam keseharian juga meningkat. Mulai dari peralatan makan bambu, kosmetik organik atau vegan, pembersih rumah tangga berbahan alami, hingga lampu LED hemat energi, pilihan produk yang lebih bersahabat dengan bumi semakin beragam. Menariknya, cukup banyak anak muda yang bersedia membayar lebih mahal untuk produk ramah lingkungan, menunjukkan adanya komitmen nilai di balik pilihan konsumsi mereka. Meskipun begitu, frekuensi pembelian produk ramah lingkungan masih bervariasi, menunjukkan adanya ruang untuk pertumbuhan dan konsistensi.
Tren lainnya yang turut mewarnai gaya hidup hijau ini meliputi meningkatnya minat pada pola makan berbasis nabati (plant-based diet) karena alasan kesehatan dan lingkungan, praktik berkebun di perkotaan (urban farming), adopsi gaya hidup minimalis untuk mengurangi konsumsi berlebih, serta dukungan terhadap produk lokal yang dianggap lebih berkelanjutan.
Munculnya beragam tren ini, mulai dari fashion hingga pilihan makanan dan transportasi, menandakan bahwa keberlanjutan tidak lagi dipandang sebagai isu tunggal, melainkan telah terintegrasi secara holistik ke dalam berbagai aspek gaya hidup anak muda. Ini bukan hanya tentang melakukan satu tindakan ramah lingkungan, tetapi tentang membangun keseluruhan cara hidup yang lebih sadar dan bertanggung jawab.
Meskipun kepedulian lingkungan menjadi pendorong utama, faktor “keren” dan kesesuaian dengan identitas diri juga memainkan peran penting dalam adopsi massal di kalangan anak muda. Thrifting, misalnya, tidak hanya mengurangi limbah tetapi juga menawarkan keunikan gaya. Begitu pula dengan gerakan zero waste yang seringkali dikemas secara kreatif dan estetis di media sosial, menjadikan keberlanjutan sebagai sesuatu yang aspiratif, bukan sekadar kewajiban.
Namun, di tengah antusiasme ini, terdapat pula indikasi adanya kesenjangan antara kesadaran yang tinggi dan tindakan yang konsisten. Data survei menunjukkan dukungan yang kuat terhadap produk ramah lingkungan, namun praktiknya masih bervariasi. Hal ini mengisyaratkan bahwa menerjemahkan niat baik menjadi kebiasaan sehari-hari yang berkelanjutan masih menjadi tantangan tersendiri.
Kisah nyata dari anak bangsa
Di balik tren-tren keren tadi, ada cerita-cerita inspiratif dari anak muda Indonesia yang nggak cuma ngomong, tapi beneran bergerak. Mereka adalah bukti nyata bahwa usia muda bukanlah halangan untuk membuat perubahan. Aksi mereka, sekecil apapun, telah membawa dampak signifikan dan menginspirasi banyak orang.
Salah satu nama yang belakangan viral adalah Pandawara Group. Kelompok yang terdiri dari lima pemuda asal Bandung ini—Gilang, Ikhsan, Rafly, Rifqi, dan Agung—awalnya merasa resah karena lingkungan tempat tinggal mereka sering dilanda banjir akibat tumpukan sampah di sungai. Berangkat dari pengalaman pribadi yang tidak menyenangkan itu, mereka memutuskan untuk turun tangan membersihkan selokan dan sungai di sekitar mereka, awalnya hanya dengan peralatan sederhana dan modal pribadi.
Yang membuat Pandawara Group unik adalah cara mereka memanfaatkan kekuatan media sosial, terutama TikTok dan Instagram. Mereka merekam aksi bersih-bersih sampah mereka—seringkali di lokasi sungai atau pantai yang sangat kotor—dan mengunggahnya dengan gaya yang menarik perhatian anak muda. Konten mereka viral, tidak hanya menampilkan kondisi lingkungan yang memprihatinkan, tetapi juga mengajak masyarakat dan netizen untuk ikut serta dalam aksi bersih-bersih. Gerakan “one day one trash bag” dan program kunjungan ke sekolah (Pandawara go to school) juga mereka galakkan untuk menanamkan kepedulian lingkungan sejak dini.
Aksi mereka tak selalu mulus; terkadang mereka menghadapi penolakan dari warga setempat. Namun, kegigihan mereka membuahkan hasil. Pandawara Group meraih berbagai penghargaan, diundang bertemu Presiden, bahkan mendapat kesempatan belajar pengelolaan sampah di Denmark, membuktikan bahwa kepedulian yang diwujudkan dalam aksi nyata bisa menginspirasi dan membawa perubahan.
Jauh sebelum Pandawara viral, ada kakak beradik asal Bali, Melati dan Isabel Wijsen. Saat mereka baru berusia 12 dan 10 tahun, terinspirasi dari pelajaran tentang tokoh-tokoh perubahan dunia, mereka memutuskan bahwa mereka tidak perlu menunggu dewasa untuk bertindak. Melihat masalah sampah plastik yang menggunung di pulau dewata, mereka mendirikan gerakan “Bye Bye Plastic Bags” (BBPB) dengan satu tujuan ambisius: menjadikan Bali pulau bebas plastik sekali pakai.
Selain mereka, masih banyak lagi anak muda inspiratif lainnya. Ada Salsabila Khairunnisa yang mendirikan platform Jaga Rimba untuk menyuarakan isu perlindungan hutan dan hak masyarakat adat, bahkan melakukan aksi ‘Mogok Sekolah untuk Hutan’ di depan gedung KLHK. Ada Rafa Jafar yang sejak kecil fokus pada bahaya sampah elektronik (e-waste), menulis buku, dan menciptakan Dropbox E-Waste. Ada juga Aeshnina Azzahra, aktivis cilik yang lantang menyuarakan isu sampah plastik, dan Zidane, penggagas Green Generation Indonesia di Balikpapan yang aktif menanam mangrove meski pernah dicibir teman-temannya. Komunitas seperti Pepelingasih, Sorong Peduli Sampah, dan Ourconservasea juga menunjukkan semangat kolektif anak muda di berbagai daerah untuk menjaga lingkungan mereka.
Kisah-kisah ini menunjukkan beberapa pola menarik. Banyak dari inisiatif ini lahir dari pengalaman pribadi yang bersentuhan langsung dengan masalah lingkungan. Keterhubungan personal ini tampaknya menjadi bahan bakar motivasi yang sangat kuat. Selain itu, para aktivis muda ini sangat mahir memanfaatkan platform digital. Mereka tidak hanya menggunakannya untuk menyebarkan kesadaran, tetapi juga untuk mengorganisir aksi nyata dan membangun komunitas. Ini menunjukkan pemahaman mendalam tentang bagaimana menerjemahkan keterlibatan online menjadi dampak offline.
Terakhir, spektrum aksi mereka sangat luas, mulai dari perubahan gaya hidup individu seperti yang diadvokasi Rafa Jafar, mobilisasi komunitas ala Pandawara, hingga advokasi kebijakan seperti yang dilakukan Melati dan Isabel. Ini menunjukkan bahwa ada banyak jalan bagi anak muda untuk berkontribusi sesuai dengan minat dan kapasitas masing-masing.
Apa sebenarnya yang mendorong gelombang semangat hijau di kalangan anak muda Indonesia ini? Mengapa mereka rela meluangkan waktu, tenaga, bahkan kadang menghadapi cibiran, demi gaya hidup yang lebih ramah lingkungan? Jawabannya ternyata kompleks dan berlapis, merupakan perpaduan antara kesadaran global, pengaruh digital, hingga dorongan personal.
Motivasi paling mendasar adalah kesadaran akan krisis iklim dan lingkungan yang semakin nyata. Generasi Z tumbuh di era di mana isu pemanasan global, polusi plastik, dan kerusakan ekosistem bukan lagi berita jauh, melainkan kenyataan yang mereka lihat dan rasakan dampaknya. Mereka terpapar informasi tentang bagaimana gaya hidup konsumtif berkontribusi pada masalah ini dan menyadari bahwa masa depan merekalah yang paling terancam jika tidak ada perubahan. Kesadaran ini seringkali diperkuat oleh pendidikan lingkungan yang mereka dapatkan, baik formal maupun informal.
Pengaruh media sosial dan tren global memainkan peran yang sangat signifikan. Paparan terhadap informasi, kampanye lingkungan global, dan gaya hidup berkelanjutan yang dibagikan melalui platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube membentuk kesadaran dan menginspirasi tindakan. Influencer lingkungan dan gaya hidup sehat memiliki pengaruh besar dalam memotivasi pengikut mereka untuk mencoba praktik-praktik baru, mulai dari diet nabati hingga penggunaan produk ramah lingkungan. Media sosial menjadi jendela dunia yang memperlihatkan bahwa gerakan ini terjadi secara global, membuat anak muda Indonesia merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar.
Ada pula keinginan kuat untuk berkontribusi dan menciptakan perubahan positif. Mereka tidak ingin hanya menjadi penonton pasif terhadap kerusakan lingkungan, melainkan ingin menjadi bagian dari solusi. Rasa tanggung jawab terhadap masa depan bumi mendorong mereka untuk mengambil tindakan nyata, sekecil apapun itu. Bagi sebagian, motivasi ini bahkan meluas ke pilihan karir, di mana mereka berharap bisa bekerja di perusahaan yang memiliki komitmen terhadap perubahan positif bagi dunia.
Aspek kesehatan dan kesejahteraan pribadi juga menjadi faktor pendorong. Banyak praktik ramah lingkungan yang sejalan dengan gaya hidup sehat, seperti lebih banyak berjalan kaki atau bersepeda, mengonsumsi makanan organik atau nabati, dan mengurangi paparan terhadap bahan kimia berbahaya. Di era di mana kesadaran akan kesehatan fisik dan mental semakin meningkat, gaya hidup berkelanjutan menawarkan pendekatan holistik untuk hidup lebih baik.
Selain itu, gaya hidup ramah lingkungan juga menjadi sarana ekspresi identitas dan nilai-nilai pribadi. Memilih thrifting bukan hanya soal hemat, tapi juga tentang menampilkan gaya unik yang berbeda dari mainstream. Mengadopsi zero waste bisa menjadi cara menunjukkan komitmen pada nilai-nilai keberlanjutan. Bagi sebagian anak muda, gaya hidup ini bahkan dianggap “keren” dan menjadi bagian dari citra diri yang ingin mereka proyeksikan. Kesesuaian dengan kelompok teman sebaya (peer group) juga bisa menjadi motivasi.
Terakhir, faktor ekonomi tidak bisa diabaikan. Meskipun beberapa produk ramah lingkungan bisa lebih mahal, banyak praktik berkelanjutan yang justru bisa menghemat uang. Thrifting jelas lebih murah daripada membeli baju baru. Mengurangi konsumsi secara umum, membawa bekal minum atau makanan sendiri, serta menghemat penggunaan energi dan air dapat memangkas pengeluaran bulanan. Bagi anak muda yang mungkin memiliki keterbatasan finansial, aspek penghematan ini menjadi daya tarik yang kuat.
Jalan terjal menuju lestari
Meskipun semangat untuk hidup lebih hijau begitu membara, perjalanannya tidak selalu mulus. Anak muda Indonesia yang mencoba menerapkan gaya hidup ramah lingkungan seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari lingkungan sekitar. Mengakui adanya hambatan ini penting, bukan untuk mematahkan semangat, tetapi untuk mencari solusi bersama.
Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan akses dan infrastruktur pendukung. Tidak di semua tempat mudah menemukan produk ramah lingkungan atau toko yang menjual barang tanpa kemasan (bulk store). Infrastruktur pengelolaan sampah, terutama fasilitas pemilahan dan daur ulang yang memadai, juga masih kurang di banyak daerah. Kondisi ini membuat pilihan berkelanjutan menjadi lebih sulit untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan di daerah yang dianggap berhasil seperti Banyumas, tata kelola sampahnya dinilai masih memiliki kelemahan dalam hal regulasi, kelembagaan, dan pendanaan.
Biaya juga bisa menjadi penghalang. Meskipun beberapa praktik seperti thrifting atau mengurangi konsumsi bisa menghemat uang, produk ramah lingkungan spesifik (misalnya, makanan organik, peralatan hemat energi) terkadang memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan alternatif konvensionalnya. Bagi pelajar atau pekerja muda dengan anggaran terbatas, perbedaan harga ini bisa menjadi pertimbangan serius.
Faktor kenyamanan dan kerumitan seringkali menjadi batu sandungan. Kebiasaan lama yang mengandalkan produk sekali pakai memang terasa lebih praktis. Mengubah rutinitas, seperti harus selalu ingat membawa botol minum atau wadah makanan, memilah sampah, atau mencari tempat daur ulang, dianggap merepotkan oleh sebagian orang. Mengubah kebiasaan yang sudah mendarah daging memang membutuhkan usaha dan waktu.
Tekanan sosial dan kurangnya dukungan juga bisa menjadi tantangan. Tidak jarang anak muda yang mencoba hidup berbeda justru mendapat cibiran atau dianggap aneh (“sok suci” atau “sok pelestari lingkungan”) oleh teman sebaya atau bahkan keluarga. Di tingkat yang lebih luas, resistensi terhadap perubahan dari komunitas lokal atau kurangnya kebijakan pemerintah yang kuat dan mendukung dapat menghambat upaya kolektif.
Melihat tantangan-tantangan ini, menjadi jelas bahwa banyak hambatan terbesar bersifat sistemik, bukan sekadar kurangnya niat baik individu. Ketiadaan infrastruktur yang memadai, pilihan yang tidak nyaman karena desain sistem yang ada, dan kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung menciptakan rintangan signifikan yang tidak dapat diatasi hanya dengan kemauan pribadi. Selain itu, ada kesenjangan antara persepsi tentang sulitnya memulai gaya hidup ini dengan kenyataan bahwa banyak langkah awal sebenarnya cukup sederhana (seperti membawa tas belanja atau botol minum).
Tantangan psikologis untuk mengubah kebiasaan dan mengatasi rasa “repot” seringkali lebih besar daripada kesulitan praktisnya itu sendiri. Faktor ekonomi juga memiliki dua sisi: biaya bisa menjadi penghalang untuk beberapa pilihan, tetapi juga bisa menjadi motivator kuat untuk pilihan lain seperti thrifting atau mengurangi konsumsi. Hal ini menyoroti pentingnya isu aksesibilitas dan keterjangkauan agar gerakan ini bisa lebih inklusif.
- Membandingkan pengelolaan sampah di Bandung dan Jakarta, pemilahan seharusnya jadi prioritas
 Pemilahan sampah dari sumbernya merupakan langkah yang lebih berkelanjutan dan berdampak sistemik, daripada pembakaran.
Pemilahan sampah dari sumbernya merupakan langkah yang lebih berkelanjutan dan berdampak sistemik, daripada pembakaran. - Deteksi dini lupus, penyakit autoimun ini bisa dikendalikan
 Deteksi dini lupus sangat penting. Ketahui gejala dan cara mengendalikannya untuk mencegah dampak serius penyakit autoimun.
Deteksi dini lupus sangat penting. Ketahui gejala dan cara mengendalikannya untuk mencegah dampak serius penyakit autoimun. - Absennya penerapan otonomi khusus Papua membuat hak masyarakat adat terus terpinggirkan
 Putusan terbaru Mahkamah Agung soal masyarakat adat Suku Awyu menjadi sorotan ketidakadilan Otonomi Khusus Papua.
Putusan terbaru Mahkamah Agung soal masyarakat adat Suku Awyu menjadi sorotan ketidakadilan Otonomi Khusus Papua. - Unpad terlibat uji klinik kandidat vaksin TBC di tengah tingginya kasus di Indonesia
 Fakultas Kedokteran Unpad melakukan uji klinik vaksin TBC M72 untuk melawan masalah kesehatan serius di Indonesia.
Fakultas Kedokteran Unpad melakukan uji klinik vaksin TBC M72 untuk melawan masalah kesehatan serius di Indonesia. - Mengolah limbah organik ampas kopi menjadi biogas
 Biogas sebagai sumber energi alternatif menjadi jawaban untuk mengurangi dampak krisis iklim karena pembakaran bahan bakar fosil.
Biogas sebagai sumber energi alternatif menjadi jawaban untuk mengurangi dampak krisis iklim karena pembakaran bahan bakar fosil. - Tujuh spesies baru lobster air tawar di Papua Barat ditemukan tim peneliti UGM
 Penemuan spesies baru lobster menunjukkan Papua adalah hotspot keanekaragaman hayati yang masih menyimpan banyak misteri.
Penemuan spesies baru lobster menunjukkan Papua adalah hotspot keanekaragaman hayati yang masih menyimpan banyak misteri.