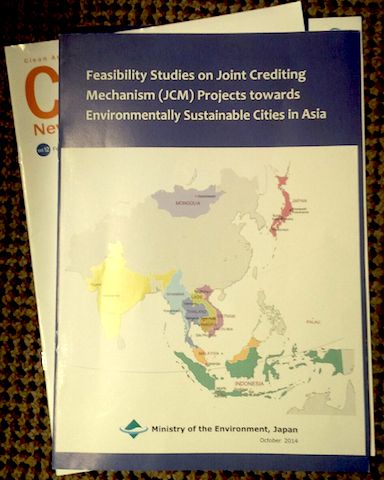Ekuatorial, Lima – Jepang menawarkan Joint Crediting Mechanism sebagai alternatif mekanisme pembangunan bersih. Lebih sederhana, lebih cepat, tetapi tingkat investasinya masih dikeluhkan perusahaan.
Pada konferensi iklim COP20 di Lima, Peru, Badan Kerjasama Internasional Jepang atau JICA memperkenalkan kembali Joint Crediting Mechanism (JCM)/ Bilateral Offset Credit Mechanism (BOCM), sebagai pasar karbon alternatif selain mekanisme pembangunan bersih (Clean Development Mechanism) yang sudah lebih dulu dikembangkan, sebagai bagian dari isi Protokol Kyoto sejak tahun 1997.
Sayangnya, dalam perjalanan CDM dianggap kurang berhasil karena dinilai oleh banyak negara berkembang, seperti juga tampak dalam laporan UNEP tentang CDM di Asia Tenggara, terlalu birokratis, rumit dan membutuhkan proses yang lama untuk mendapatkan Certified Emission Reductions (CERs) sebagai tanda sah untuk menjual karbon.
Sekarang Jepang menawarkan JCM/BOCM yang lebih sederhana, karena hanya terdiri dari dua pihak yaitu Jepang dan perusahaan dari negara peserta penerima JCM. Proses untuk mendapatkan sertifikat kredit karbon terhitung cepat, antara 1-2 tahun. Bandingkan dengan CDM yang dikelola secara global di bawah UNFCCC yang melibatkan multipihak dan prosesnya relatif lama. Sampai Januari 2014, JCM telah ditandatangani 10 negara dan diharapkan akan ada tambahan 6 negara sampai tiga tahun mendatang.
“Saat ini ada 13 perusahaan dari Indonesia yang terdaftar dalam JCM dan satu perusahaan sudah memasuki tahap monitoring dan evaluasi perhitungan untuk mendapatkan sertifikasi kredit karbon,” kata Ratu Keni Atika, Monitoring, Evaluation, Dissemination Specialist dari Sekretariat JCM Indonesia kepada Ekuatorial di Lima Peru, hari Rabu (3/12).
Perusahaan tekstil PT Primatexco Indonesia yang berbasis di Batang, Jawa Tengah, yang mendaftarkan diri pada Juni 2014 lalu, adalah perusahaan pertama yang telah memasuki tahap MRV (monitoring, reporting, and verification) untuk mendapatkan kredit karbon. Jika Primatexco lolos, mereka akan menjadi perusahaan pertama mendapatkan kredit karbon dari JCM.
Ratu optimistis banyak perusahaan Indonesia akan mendapatkan sertifikat kredit karbon dari JCM karena prosesnya jauh lebih mudah dan cepat. Ia menjelaskan, setiap perusahaan yang berminat hanya perlu mendaftarkan dirinya dan mengajukan usulan penggunaan teknologi rendah karbon yang mereka inginkan. Semua emisi dari skema JCM ini merupakan offset untuk pemerintah Jepang dan akan dihitung sebagai bagian dalam pengurangan emisi mereka.
JICA dan pemerintah Indonesia akan mencari partner perusahaan di Jepang, yang sesuai dengan karakteristik dan jenis teknologi rendah karbon yang diinginkan oleh mitranya di Indonesia. Lalu mereka bersama-sama menetapkan reference level atau tingkat emisi acuan, berdasarkan teknologi yang paling efisien yang tersedia di pasar Indonesia. “Jadi, tingkat emisinya bukan dari teknologi lama yang sudah dipakai oleh perusahaan, tetapi emisi dari teknologi paling maju yang ada di pasar,”kata Ratu.
Contohnya, jika satu perusahaan di Indonesia ingin mengadopsi JCM untuk mengurangi emisi dari generator yang mereka pakai, maka bersama mitranya dari Jepang, mereka akan mencari generator yang emisinya paling rendah yang saat ini dijual di pasar Indonesia. Lalu, generator di pasar inilah yang emisnya dipakai sebagai acuan. Perusahaan di Indonesia dan Jepang akan berusaha mencari atau mengembangkan teknologi generator yang emisinya lebih rendah lagi, lalu selisih emisinya itulah yang akan dihitung dan mendapatkan sertifikat reduksi karbon.
Pemilihan teknologi paling canggih di pasar sebagai acuan emisi, lanjut Ratu, adalah upaya negara-negara peserta JCM, agar tidak menjadi negara buangan untuk teknologi yang sudah kedaluarsa dan tinggi emisi karbonnya. Jika teknologi sejenis sudah didapatkan tingkat emisinya, maka dimulailah proses untuk memilih teknologi rendah karbon yang akan dipakai.
Syarat JCM, semua teknologi dalam skema ini harus dipasok oleh perusahaan-perusahaan dari Jepang, mulai dari teknologi penghematan energi, efisiensi transportasi, energi alternatif, pengolahan limbah, penghancuran CFC, dan lain-lain.
Namun, perusahaan dalam negeri masih mengeluhkan soal tingginya investasi yang harus mereka tanamkan dalam skema ini. Durain Parmanoan dari Semen Indonesia mengaku mereka menginvestasikan 80% anggaran dalam pembelian teknologi itu sementara koleganya JFE Engineering Corp. dari Yokohama, Jepang hanya 20%. “Kami kan masih harus mengeluarkan uang untuk monitoring berkala dan perawatan teknologi setelah proyek ini selesai. Seharusnya share kami jauh di bawah itu,”katanya,”Apalagi skema ini dalam rangka komitmen negara maju mengurangi emisinya.”
Bila Semen Indonesia berhasil, jumlah emisi yang dikurangi dari boiler, turbin, dan generator akan mencapai 130 ribu ton/tahun. Saat ini, untuk satu ton semen, mereka masih menghasilkan sekitar 1 ton karbon dioksida. “Kami akan segera mencapai tingkat emisi 700 kg per ton semen,”ujarnya. Dan pada tahun 2020 menurut Durain, industri semen diharapkan mampu menekan emisinya hingga mencapai 650 kg CO2/ton semen.
Hambatan lain dari sektor semen adalah kegandrungan perusahaan kontraktor memakai Semen Tipe I yang berkualitas paling bagus, tetapi menghasilkan banyak emisi dalam produksinya. Padahal, kata Durain, saat ini sudah ada jenis Portland Composite Cement yang tak kalah kualitasnya, tetapi emisinya jauh lebih rendah.
IGG Maha Adi (Lima, Peru)